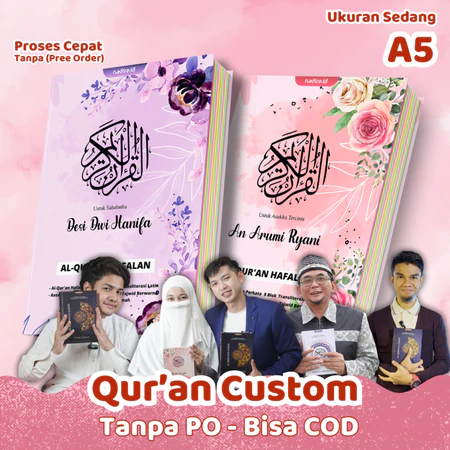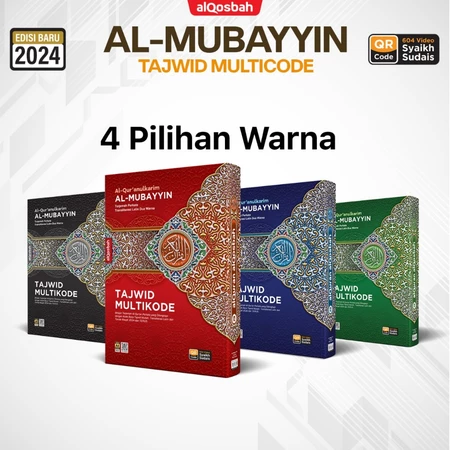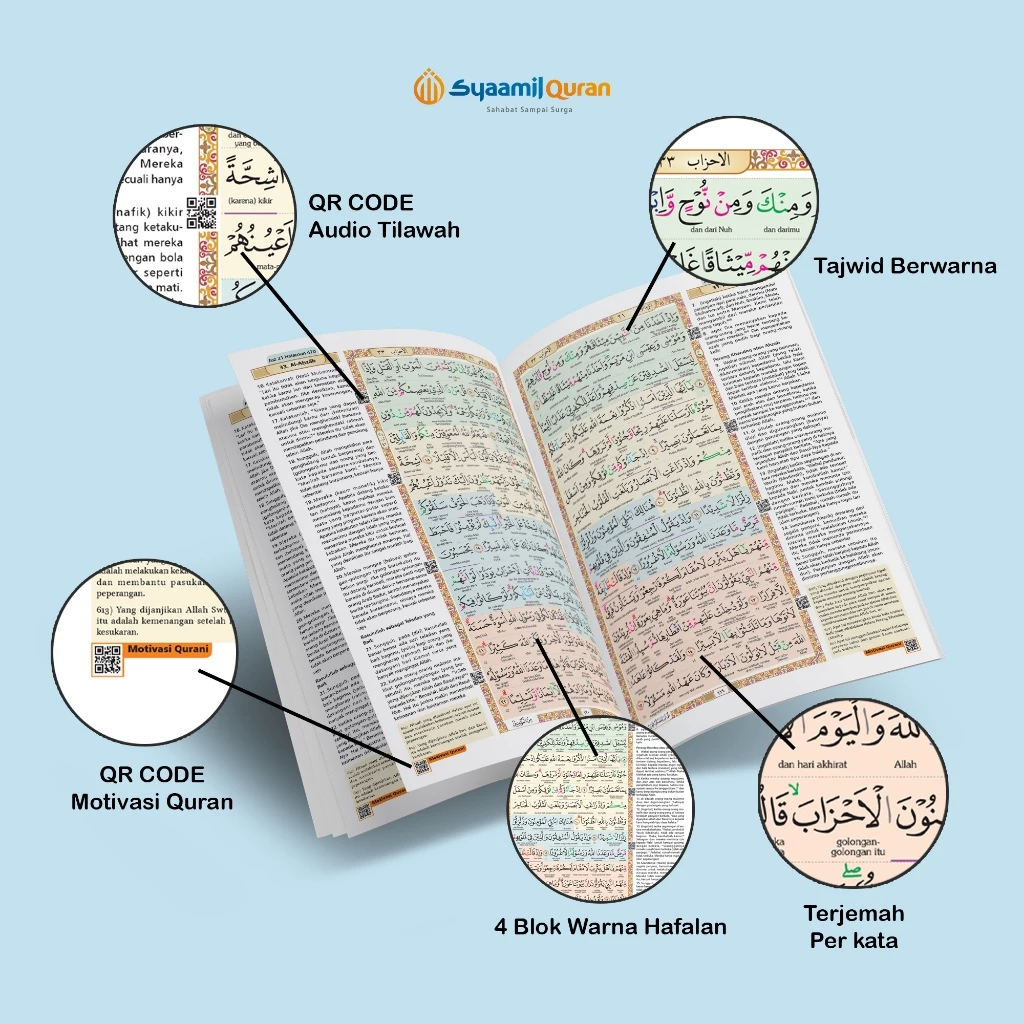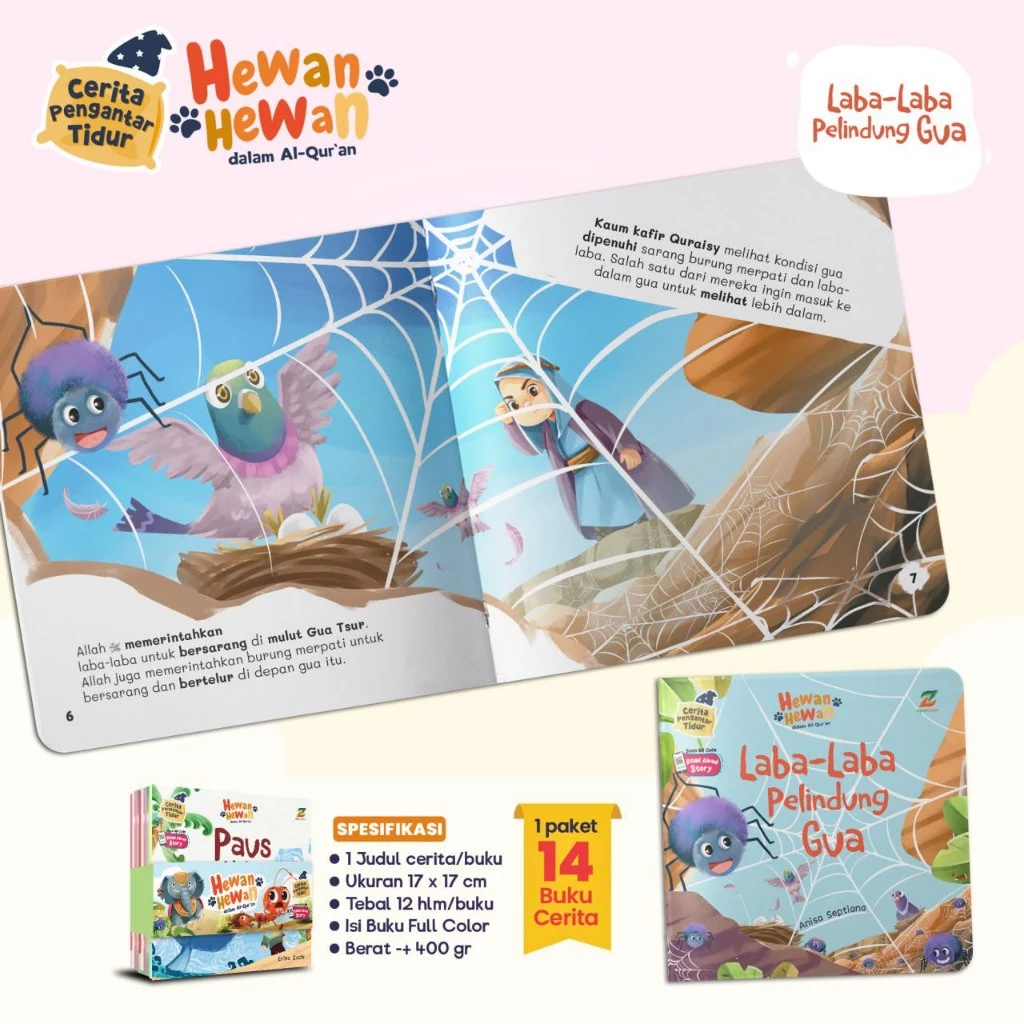Teori Resepsi Kembali Ke Sistem Hukum Indonesia
 |
| Penulis adalah Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan |
Opini Oleh: Albar Sentosa Subari*)
JENDELAKITA.MY.ID - Istilah
Resepsi di zaman kolonial maupun awal pasca kemerdekaan sangatlah populer di
kalangan studi ilmu hukum.
Sekedar mengingatkan bahwa teori Resepsi mengalami Pase
perkembangan setidak tidaknya ada 3 phase makna.
Pertama teori Resepsi dicetuskan oleh sarjana Belanda
bernama Prof. Van Keyzer dan Prof. Van den Bosch. Yang mengatakan bahwa hukum
adat suatu masyarakat yang beragama Islam akan sama seperti hukum agama
masyarakat tersebut ( teori ini disebut teori receptio in complektio).
Di masa itu sedang populer penelitian tentang hukum adat.
Prof. Van den Bosch akhirnya menemukan kompilasi tentang hukum adat yang di
Sumatera Selatan di sebut Simbur Cahaya.
Kedua, teori Resepsi yang menentang teori Resepsi yang
disampaikan oleh Prof. Van Keyzer dan Prof Van den Bosch.
Adalah teori dari Prof. Snouck Hurgronje juga berkebangsaan
Belanda yang mengatakan bahwa yang benar adalah Hukum agama/Islam baru diterima
atau berlaku setelah diresepsi oleh Hukum Adat (Teori kedua ini disebut teori
receptio).
Ketiga, dari kedua pendapat tersebut lahirlah Teori dari
Prof Hazairin guru besar hukum adat dan hukum Islam di Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, bersama sama dengan Sayuti Thalib, SH, mengeluarkan buku
berjudul Reseptio a contrario, bahwa mengatakan hukum adat itu baru berlaku
setelah diresepsi oleh Hukum agama/Islam.
Sehingga beliau menggunakan istilah " teori iblis
" untuk membantah teorinya Snouck Hurgronje tersebut.
Kembali ke fokus tulisan kita apa yang dimaksudkan dengan
Teori Resepsi kembali ke sistem hukum Indonesia.
Di sini penulis secara kajian teori mengatakan bahwa teori
Resepsi tersebut lahir kembali namun pokok bahasan menyangkut hukum adat (hukum
yang hidup dalam masyarakat) dengan hukum negara/tertulis.
Bahwa setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 23 tentang
Kitab Undang Undang Hukum Pidana, di satu sisi mengakui keberadaan hukum yang
hidup dalam masyarakat, namun di sisi yang lain pengakuan tersebut bila telah
diresepsi oleh hukum tertulis yaitu Peraturan Daerah.
Artinya hukum adat tidak
otomatis diberlakukan digali oleh seorang hakim saat menegakkan keadilan
dan kebenaran. Tapi terlebih dahulu harus telah mempunyai dasar hukumnya yaitu
peraturan daerah.
Ini menimbulkan persoalan baru bahwa tidak mudah bagi
lembaga pembuat perda untuk melakukan hal dimaksud karena banyak faktor
pemahaman dari oknum oknum yang ada di lembaga eksekutif maupun legislatif.
Apakah selama itu juga (sebelum ada perda) hukum adat yang
disebut hukum yang hidup dalam masyarakat terabaikan. Tentu ini inkonsisten
dengan nilai nilai Pancasila.
Sebagaimana disampaikan oleh Prof Dr. Suripto, SH, guru
besar hukum adat di universitas Brawijaya Malang di saat menyampaikan pidato
pengukuhan nya Hukum Adat dan Pancasila Dalam Pembinaan Hukum Nasional tahun
1956, bahwa Pancasila adalah cerminan dari Hukum Adat.
Sejalan dengan pandangan Ir Soekarno saat pidato nya tanggal
1 Juni 1945, bahwa beliau adalah seorang penggali nilai nilai hukum adat yang
akhirnya disebutkan dengan Pancasila.
Artinya di sini bahwa pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat
yang dimaknai dalam Pasal 597 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sama dengan
bunyi pasal pasal dalam aturan zaman kolonial Belanda misalnya dalam aturan 11
AB. Bahwa hukum adat baru berlaku setelah diresepsi oleh undang undang.
Di sinilah yang penulis maksud bahwa teori Resepsi kembali
ke sistem hukum Indonesia.
Kembali ke sejarah hukum Pancasila merupakan sumber dari
segala sumber hukum sebagai mana termaktub dalam Ketetapan MPRS no XX tahun
1966.
Terkait dengan penerapan otonomi daerah seluas-luasnya, maka
dalam perkembangan muncul peraturan daerah yang dibuat dalam rangka memberikan
regulasi yang mengakomodir keragaman dan kekhasan masing-masing daerah.
Namun dalam perjalanan nya banyak ditemukan peraturan daerah
yang kemudian terbukti bertentangan dengan peraturan lebih tinggi atau
dibatalkan karena tidak sejalan dengan cita cita bangsa Indonesia.
Pembentukan hukum di daerah sering hanya dipahami sebagai
perkara teknis belaka tanpa memperhatikan proses sosial budaya dan politik nya
mengakibatkan substansi nya menjadi carut marut dan inkonsisten. Tidak jarang
subtansi sebuah peraturan daerah lebih banyak hasil contekan dari daerah lain.
Dengan demikian, maka munculah perda perda yang tidak
berkualitas alias bermasalah bisa semakin menjamur (lihat Jawahir Thontowi,
2016).
Sebagai penutup dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa
dalam sistem hukum Indonesia sekarang masih menganut sistem hukum yang
diskriminatif, karena sistem hukum tertulis menjadi tujuan utama sedangkan
subsistem hukum yang hidup dalam masyarakat masih di bawah bayangan hukum
negara tertulis.
Padahal hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan cerminan
dari nilai-nilai Pancasila yang bersifat terbuka.
Karena hukum yang hidup dalam masyarakat bersifat dinamis
tidak kaku, seperti hukum tertulis. Hari ini diundang sekaligus hari itu pula
dia tertinggi (hukum yang mati).***
*) Penulis adalah
Ketua Pembina Adat Sumsel