Dari Ranah Privat Menjadi Ranah Publik Dalam Kasus Royalty
Penulis: H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. (Pengamat Hukum)
Jendelakita.my.id. - Semua orang tahu, apalagi yang pernah atau sedang mempelajari ilmu hukum, tentu memahami perbedaan antara hukum privat dan hukum publik. Secara sederhana dapat dibedakan bahwa hukum privat, atau disebut juga hukum sipil/perdata, adalah sistem hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu dalam suatu kesatuan masyarakat (bangsa) yang mengatur hak dan kewajiban dalam interaksi sosial antara sesama subjek hukum, baik individu maupun kelompok.
Sementara itu, hukum publik atau disebut juga hukum negara/penguasa adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu atau kelompok sebagai subjek hukum privat dengan negara sebagai subjek hukum publik, demi kepentingan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keduanya, baik hukum privat maupun hukum publik, dalam ilmu hukum Indonesia termasuk dalam kategori hukum positif tertulis. Di samping itu, terdapat pula hukum positif tidak tertulis, yakni hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat adat maupun masyarakat modern. Walaupun demikian, sebagian ahli berpendapat bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat bukan termasuk hukum positif.
Sebelum membahas lebih jauh mengenai perbedaan hukum privat dan hukum publik, penulis teringat pada satu kajian sejarah: mana yang lebih dahulu lahir, hukum privat atau hukum publik? Prof. Iman Sudiyat, S.H., Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sekaligus pembimbing tesis penulis, pernah menyatakan bahwa hukum publik lebih dahulu lahir dibanding hukum privat. Hal ini karena sejak seorang manusia lahir, ia sudah langsung diatur oleh hukum publik.
Keterkaitan hukum publik dengan sifat religius suatu komunitas terlihat, misalnya, dalam ajaran Islam yang mensunnahkan setiap bayi baru lahir untuk didengarkan azan dan iqamah di telinganya. Walaupun dalil ini sempat dipersoalkan sebagian kelompok, praktik tersebut menunjukkan bahwa sejak awal kehidupan manusia, sudah terdapat relasi antara subjek hukum dengan aturan yang bersifat publik dan religius. Seiring pertumbuhan, manusia yang beranjak dewasa dapat melaksanakan kewajiban dan menuntut hak, misalnya bekerja dan memperoleh upah. Oleh karena itu, dalam ilmu hukum Indonesia ditegaskan bahwa yang didahulukan adalah kewajiban baru kemudian hak, bukan sebaliknya.
Artikel ini terinspirasi dari pernyataan kontroversial mengenai kebijakan Wahana Musik Indonesia (WAMI) yang memungut royalti dari individu (subjek hukum privat) yang menikmati karya seni musisi atau penyanyi di tempat umum, seperti tempat hiburan, kendaraan umum, hingga hotel atau penginapan yang diasumsikan pasti memiliki sarana hiburan/televisi. Hal ini menimbulkan kritik karena dianggap menciderai asas kepastian hukum.
Padahal, asosiasi musisi Indonesia sudah menyatakan bahwa mereka tidak menuntut royalti atas karya seni yang dinikmati publik. Ari Lasso, misalnya, secara terbuka menyampaikan hal tersebut. Namun, WAMI tetap memberlakukan pemungutan royalti. Secara filosofis, ketentuan tentang royalti dimaksudkan untuk melindungi hak cipta seseorang atas karya seninya. Artinya, yang berhak menerima royalti adalah pencipta atau pemilik karya. Perlindungan hak cipta seharusnya menjadi kewajiban negara. Jika terjadi pelanggaran, barulah sanksi pidana dapat diberlakukan, tentunya atas aduan pencipta.
Pertanyaannya, apakah negara sudah maksimal dalam melindungi hak cipta para seniman? Seharusnya, negara terlebih dahulu menegakkan hukum hak cipta sebelum menarik pajak dari para pencipta karya. Bukan justru menarik royalti dari masyarakat umum.
Jika perlindungan hak cipta berjalan optimal, maka akan terdapat hubungan timbal balik yang sehat: negara berkewajiban melindungi hak cipta, pencipta seni berhak menerima royalti, dan masyarakat berkewajiban menghargai karya seni dengan cara membeli karya tersebut secara legal. Dengan demikian, negara mendapat hak dari kewajiban yang telah dijalankan, para musisi memperoleh imbalan atas karya mereka, dan masyarakat menikmati karya seni dengan tenang serta sah secara hukum.
Kembali pada teori mengenai sejarah hukum, kasus perseteruan antara musisi dan WAMI menunjukkan bahwa dalam konteks ini hukum publik seharusnya lebih dahulu hadir. Negara, sebagai subjek hukum publik, berkewajiban melindungi hak cipta para pencipta seni yang merupakan subjek hukum privat. Setelah itu, barulah pencipta seni berkewajiban memberikan royalti yang dipungut negara sebagai haknya. Bukan sebaliknya, di mana masyarakat umum yang tidak tahu-menahu justru dibebani pungutan royalti.
Dengan demikian, hubungan timbal balik yang ideal adalah: negara melindungi hak cipta, musisi memberikan royalti kepada negara, dan masyarakat menikmati karya seni sebagai bagian dari hak mereka sebagai warga negara. Dalam kerangka tersebut, setiap pihak menempati posisinya sesuai dengan prinsip keadilan hukum.





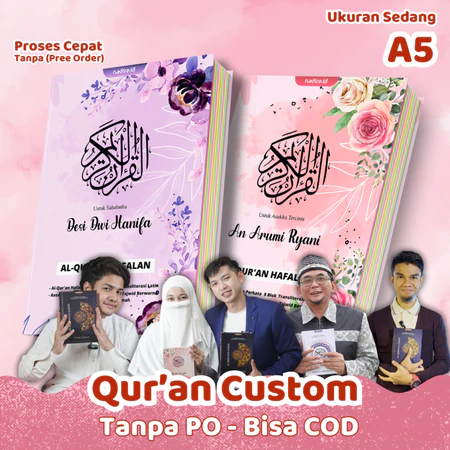
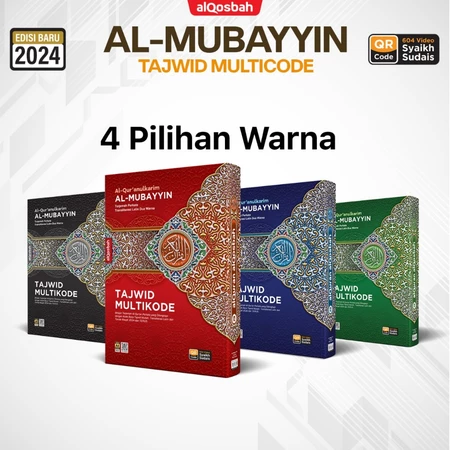
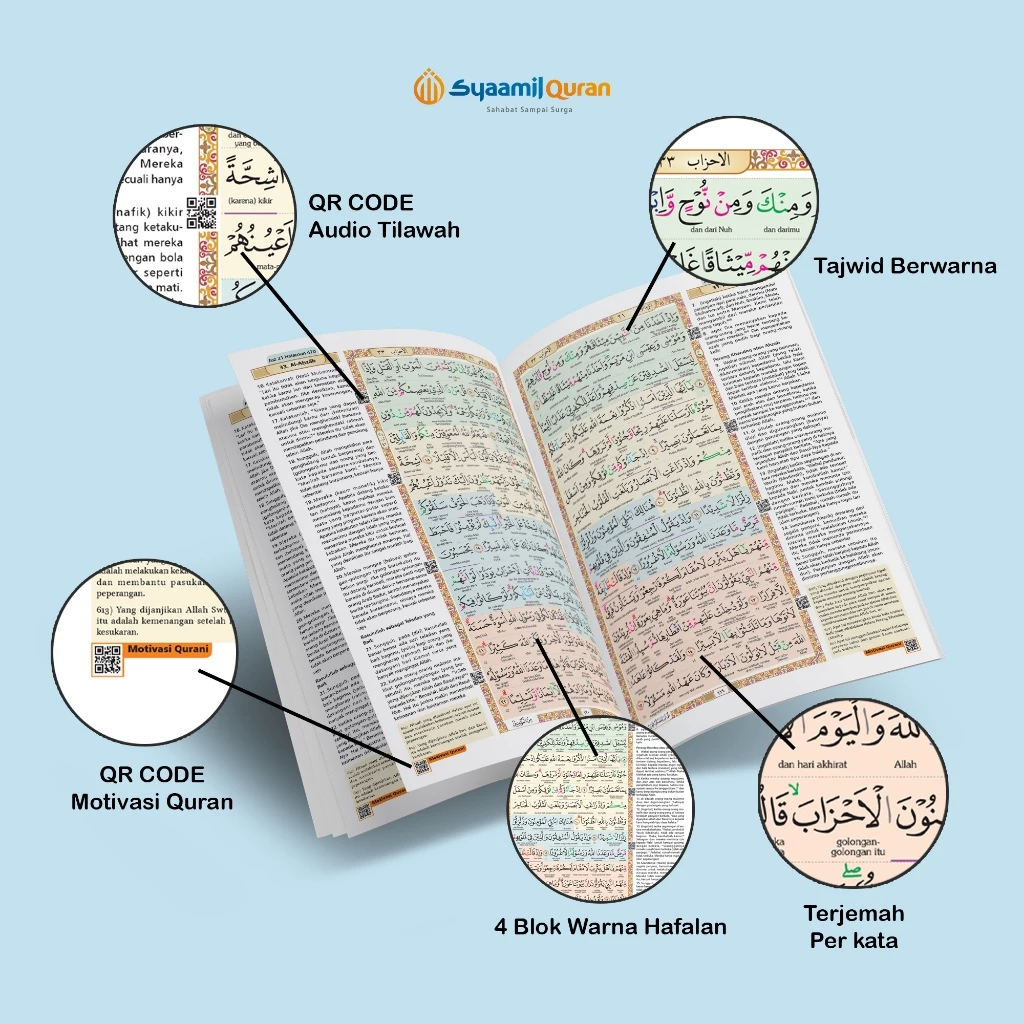
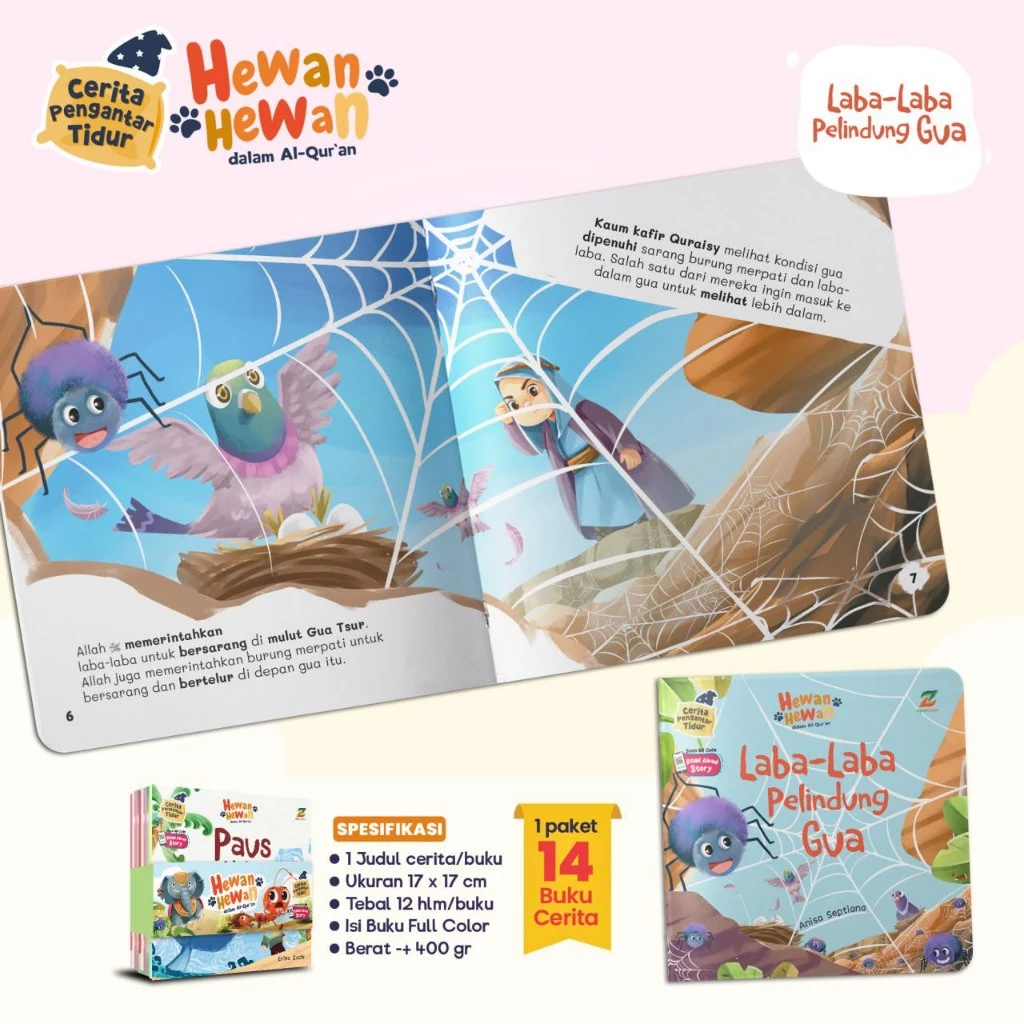

.jpg)


