Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila
Penulis: H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. (Pengamat Hukum)
Jendelakita.my.id. - Judul artikel di atas terdiri dari tiga kelompok makna. Pertama, kata Kedaulatan Rakyat; kedua, Demokrasi Pancasila; dan ketiga, Nilai-nilai Pancasila. Ketiga komponen judul tersebut jika digabungkan akan bermakna bahwa Indonesia merupakan negara yang telah berhasil mewujudkan cita hukum Indonesia. Cita hukum (Rechtsidee) tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri atas empat alinea. Khusus pada alinea keempat, terdapat rumusan Pancasila secara normatif yang diawali dengan kalimat:
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang BERKEDAULATAN RAKYAT (huruf kapital oleh penulis) dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN (huruf kapital oleh penulis), serta dengan mewujudkan KEADILAN SOSIAL (huruf kapital oleh penulis) bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pancasila perlu dipahami minimal dari tiga sisi. Pertama, dari sisi ilmu Pancasila; kedua, dari sisi yuridis kenegaraan; dan ketiga, dari sisi filsafat Pancasila. Disebut sebagai ilmu Pancasila karena: (a) objeknya adalah naskah-naskah resmi negara; (b) memiliki metode, yaitu pendekatan ilmiah terhadap objek tersebut sehingga dapat dipahami; (c) bersistem, artinya keseluruhan proses dan hasil berpikir disusun dalam satu kesatuan yang bulat dan saling berhubungan antara bagian-bagiannya; dan (d) menyediakan argumentasi atau bukti.
Adapun kaitannya dengan yuridis kenegaraan, Prof. Drs. Sunarjo Wreksosuhardjo merincikan dalam 11 butir pernyataan (Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Filsafat Pancasila, Yogyakarta, 2001). Salah satu contohnya, yang erat kaitannya dengan spesialisasi penulis di bidang hukum adat, adalah bahwa Pancasila dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu dalam arti material dan arti formal.
Pancasila dalam arti material ialah pengertian yang tetap dari sila-sila Pancasila, terlepas dari bagaimana bunyi rumusannya. Isi pengertian yang tetap dari sila-sila Pancasila ini sudah ada jauh sebelum lahirnya negara Proklamasi 17 Agustus 1945 (lihat naskah sidang BPUPK I maupun PPKI). Pancasila dalam arti material ini senantiasa hadir dalam kehidupan bangsa Indonesia sepanjang masa, diamalkan dalam adat, kebudayaan, serta agama yang dipeluk bangsa Indonesia. Jejaknya dapat ditelusuri sejak zaman Sriwijaya hingga Majapahit.
Titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah adalah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yang dijiwai dan disemangati oleh Pancasila dalam arti material. Sehari kemudian, pada 18 Agustus 1945, saat pengesahan UUD Negara Republik Indonesia, semangat dan jiwa proklamasi — yakni Pancasila — dituangkan ke dalam Pembukaan. Dengan demikian, Pancasila memperoleh bentuk dan dasar hukum resmi sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.
Inilah yang disebut Pancasila dalam arti formal, yaitu rumusannya dalam bentuk kata-kata tertentu yang memiliki kedudukan hukum sebagai dasar filsafat negara. Karena Pancasila berfungsi sebagai dasar filsafat, maka Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 menjalankan fungsinya sebagai dasar filsafat yang bersifat teoritis maupun praktis. Fungsi teoritisnya adalah sebagai pedoman untuk menemukan kebenaran sedalam-dalamnya, sedangkan fungsi praktisnya adalah sebagai pedoman untuk bertindak dan melangkah.
Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa sebelum memperoleh kedudukan formal sebagai dasar negara, Pancasila dalam arti material telah lama menjadi pandangan hidup bangsa dan diamalkan dalam adat istiadat serta agama-agama di Indonesia. Setelah UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945, pandangan hidup bangsa ini dikukuhkan sebagai dasar filsafat negara.
Dengan demikian, Pancasila yang merupakan filsafat berfungsi sebagai pedoman teoritis maupun praktis, sehingga menjadi pusat dasar dan inti dari Pembukaan UUD 1945. Artinya, seluruh isi Pembukaan UUD 1945 selain Pancasila merupakan penjelmaan dari Pancasila yang menjadi pusat, dasar, dan inti. Dengan kata lain, seluruh isi Pembukaan UUD 1945 selain Pancasila harus dapat dipulangkan kembali atau dipertanggungjawabkan kepada Pancasila sebagai pusat, dasar, dan inti. Oleh karena itu, seluruh isi Pembukaan UUD 1945 selain Pancasila wajib ditafsirkan serta diinterpretasikan dari sudut pandang Pancasila.





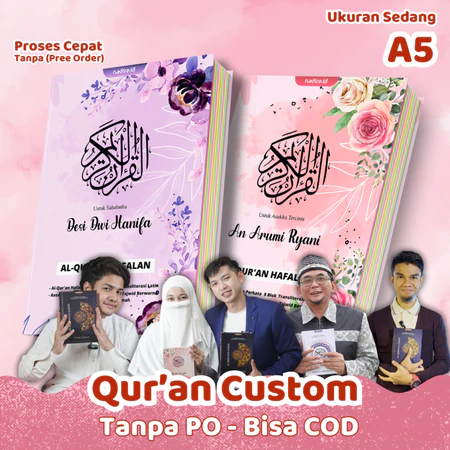
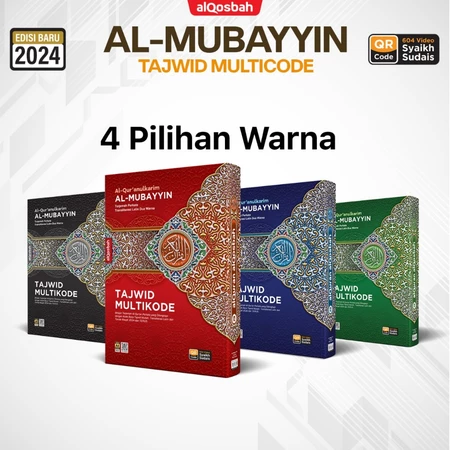
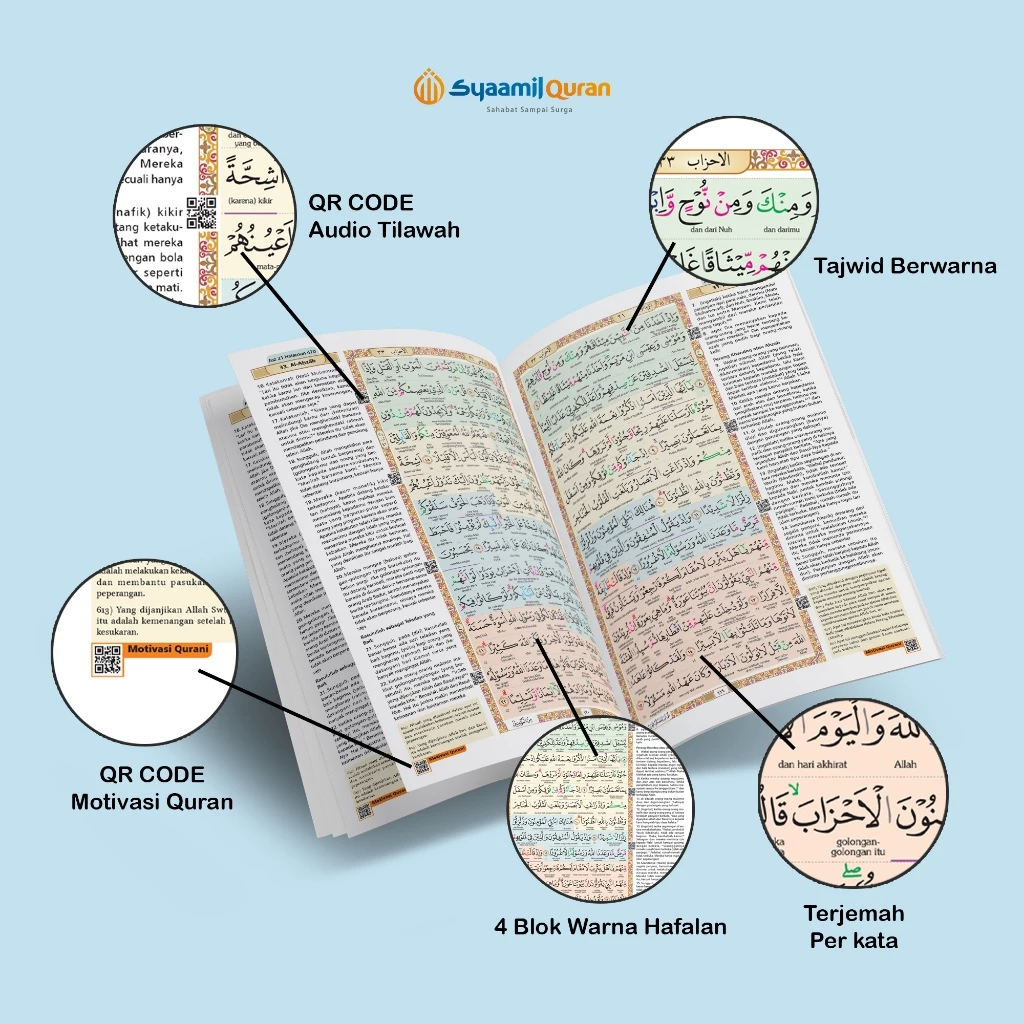
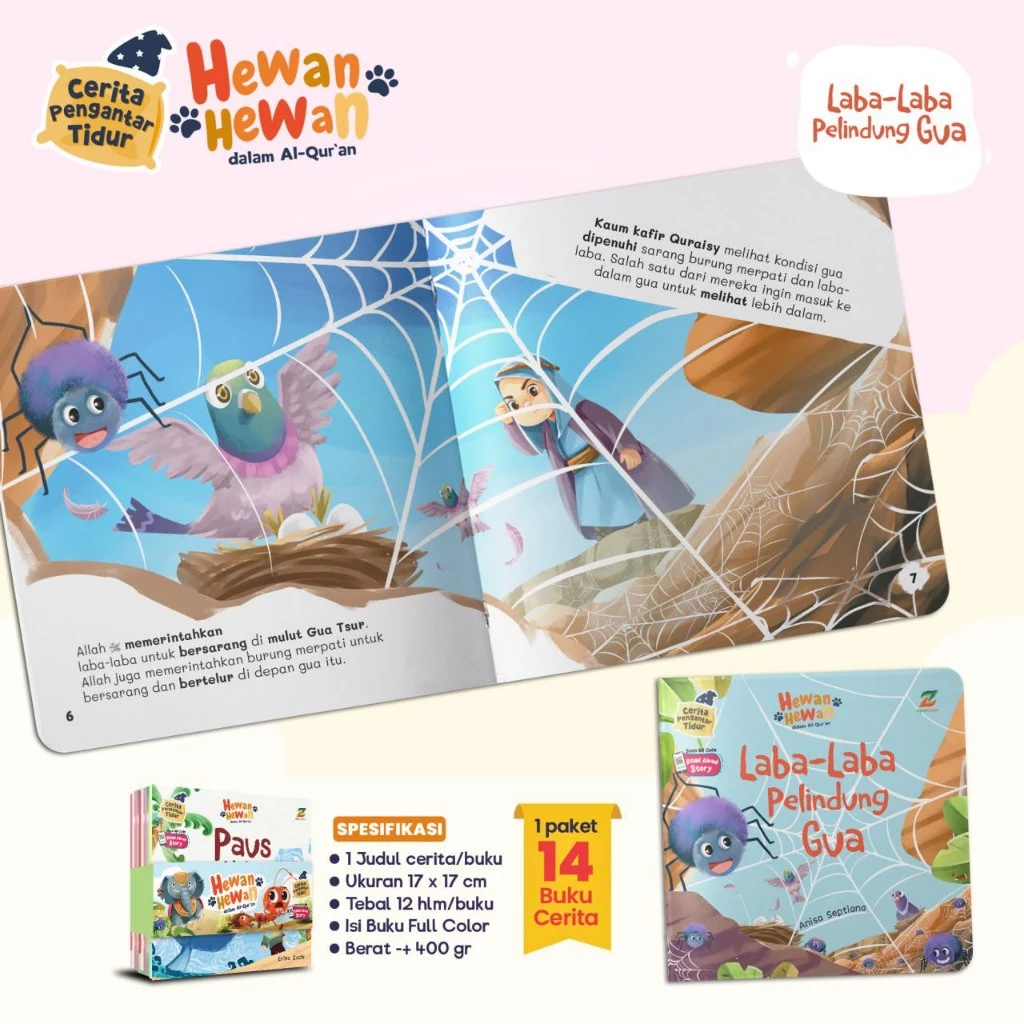

.jpg)

