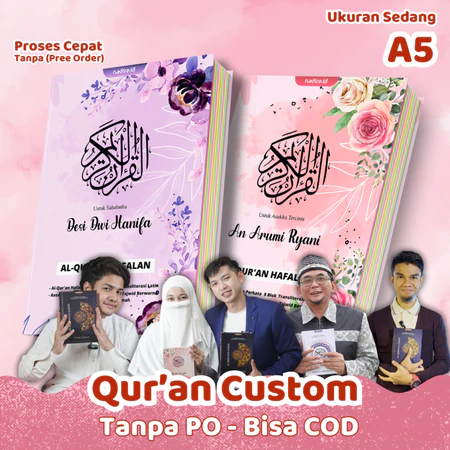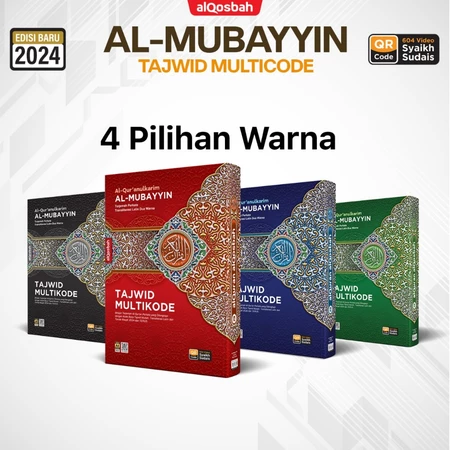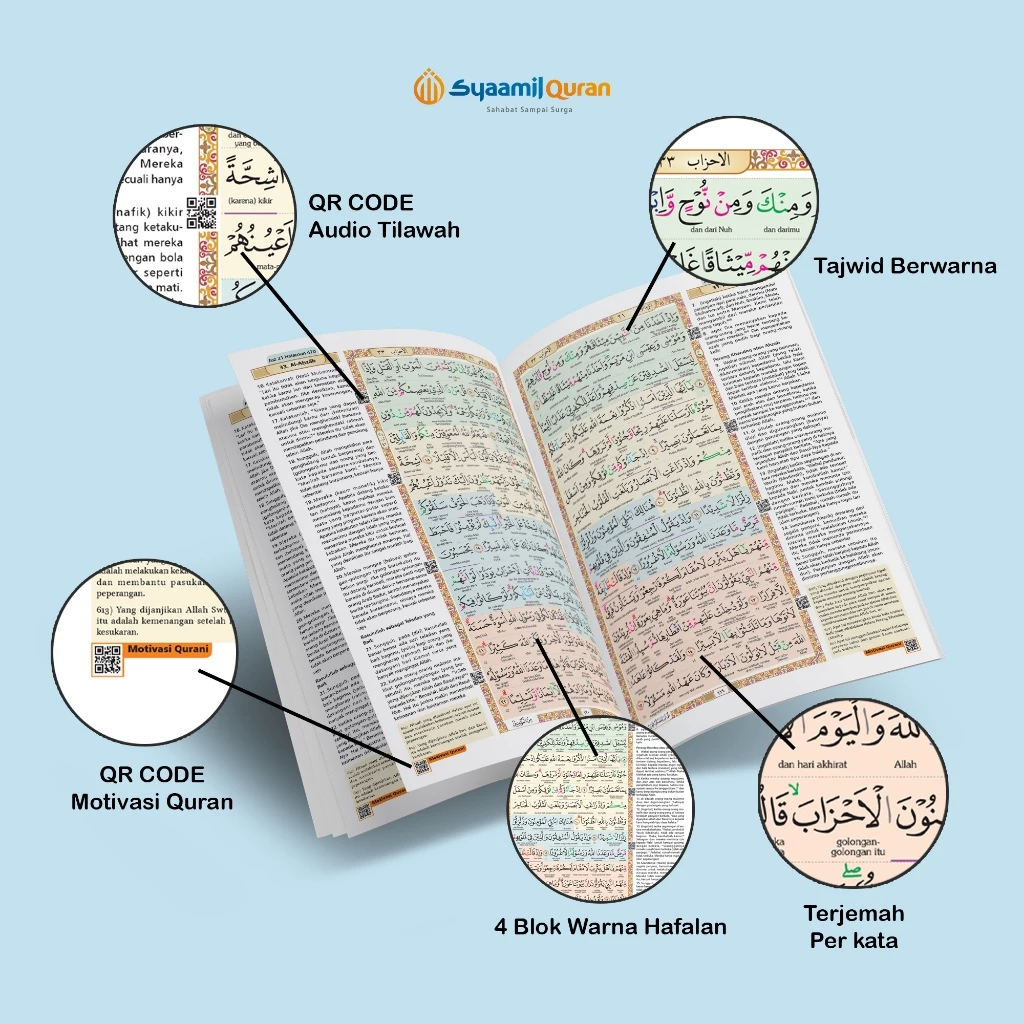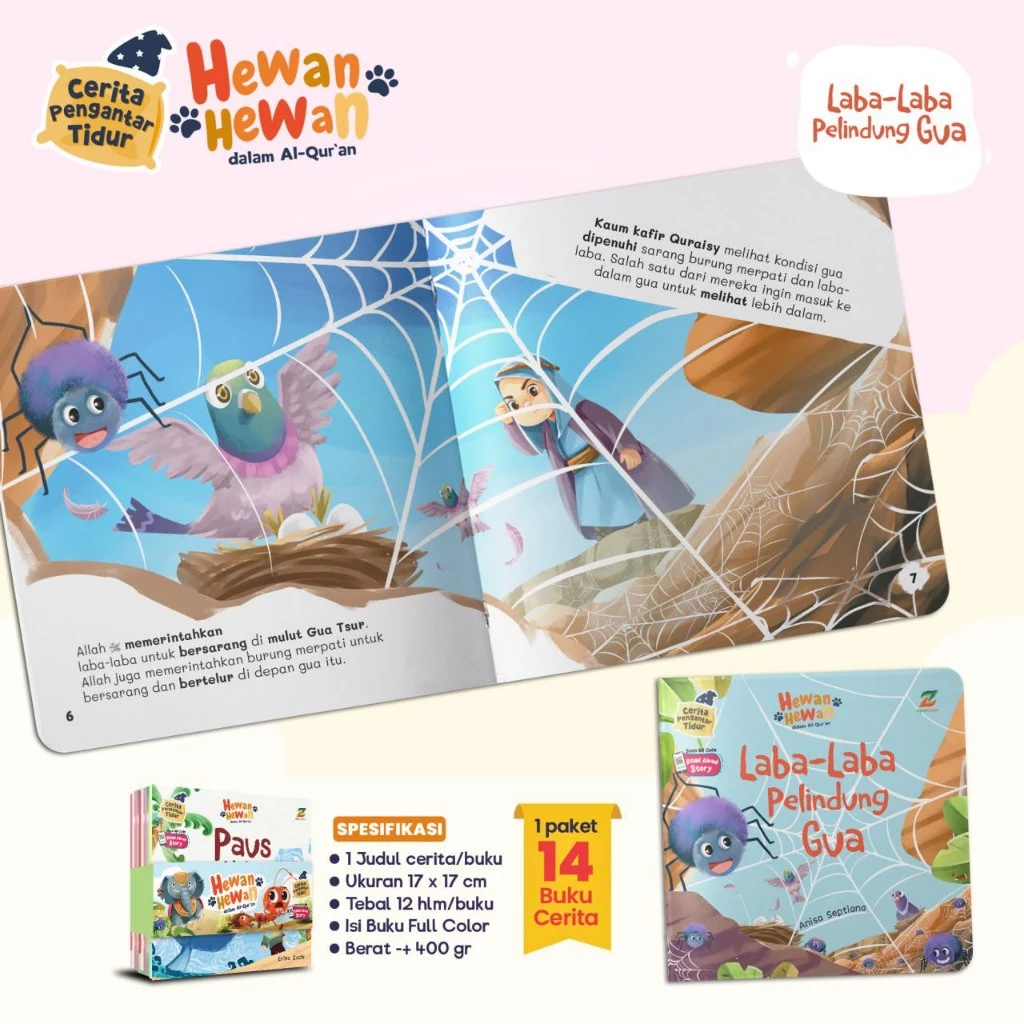Hukum dan Bahasa Hukum
Jendelakita.my.id. - Jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satunya yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, maka akan kita temukan bahwa hukum dijelaskan sebagai: (1) peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak; (2) segala undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup di dalam masyarakat (Poerwadarminta, 1976). Hukum adalah aturan atau peraturan yang mengandung norma-norma untuk mengatur kelakuan, perbuatan, tindakan, dan kehidupan masyarakat. Tanpa hukum, masyarakat akan berada dalam kekacauan. Semua aturan atau peraturan itu dinyatakan dalam bahasa, yakni bahasa hukum.
Bahasa hukum yang digunakan dalam bahasa Indonesia merupakan ragam bahasa resmi yang tunduk pada aturan atau kaidah bahasa baku atau bahasa standar. Baik bahasa maupun hukum merupakan penjelasan kehidupan manusia dalam masyarakat dan menjadi bagian dari perwujudan suatu kebudayaan dalam ruang dan waktu tertentu. Dalam hubungan antara masyarakat dan kebudayaan tertentu, bahasa dan hukum saling berkaitan, saling memengaruhi, bahkan kebudayaan dapat dianggap sebagai wujud dari masyarakat yang dipengaruhi pula oleh bahasa dan hukum (Alisjahbana, 1976). Oleh karena itu, gambaran mengenai bahasa hukum tidak dapat dilepaskan dari ciri-ciri dan struktur masyarakat serta kebudayaan secara menyeluruh.
Bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa resmi dan bahasa negara. Sebagai bahasa yang terus berkembang, bahasa Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Namun, dasar kaidah bahasanya yang berasal dari bahasa Melayu tetap dipertahankan. Oleh sebab itu, apabila kita menggunakan bahasa Indonesia dalam bidang hukum, maka penggunaannya pun harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Dalam praktiknya, kita sering menjumpai bahwa bahasa hukum Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan sifat dan struktur bahasa Indonesia yang baik. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sistem hukum Indonesia sebagian besar bersumber dari hukum tertulis peninggalan kolonial Belanda, yang menggunakan bahasa Belanda. Bahasa hukum Indonesia yang kita gunakan sering kali merupakan hasil terjemahan dari bahasa Belanda secara harfiah, tanpa mempertimbangkan idiom dan struktur bahasa Indonesia.
Kita mungkin tidak bisa sepenuhnya menghindari pengaruh bahasa Belanda, namun kita wajib berupaya agar alih bahasa tersebut sesuai dengan struktur dan ungkapan (idiom) bahasa Indonesia. Kurangnya penguasaan bahasa Indonesia oleh penerjemah sering menyebabkan terjemahan dari bahasa Belanda menjadi terlalu harfiah dan menyulitkan pemahaman terhadap makna sebenarnya. Satu persoalan lainnya adalah kecenderungan penggunaan kalimat yang terlalu panjang dalam bahasa hukum. Sebuah kalimat bisa terdiri dari ratusan kata dan puluhan baris. Kalimat-kalimat semacam ini sebenarnya dapat dipecah menjadi beberapa kalimat pendek tanpa mengubah makna keseluruhan.
Terdapat pula anggapan bahwa bahasa hukum dalam bahasa Indonesia tidak mencerminkan keaslian bahasa Indonesia, sehingga terkesan memiliki corak tersendiri yang berbeda dari bahasa Indonesia umum yang digunakan oleh masyarakat. Akibatnya, bahasa hukum menjadi sulit dipahami. Anggapan ini tampaknya benar apabila kita membaca kalimat-kalimat dalam dokumen hukum yang panjang, penuh dengan anak dan cucu kalimat. Ketika susunannya tidak teratur, makna kalimat menjadi sulit ditangkap karena tidak jelas bagian mana yang menjelaskan dan mana yang dijelaskan.
Masalah ini semakin diperburuk dengan belum adanya terjemahan resmi dari negara atas naskah-naskah hukum Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Akibatnya, kita masih mengandalkan terjemahan perseorangan yang rawan menyebabkan salah tafsir sesuai dengan pemahaman si penerjemah. Misalnya, dalam bahasa Belanda, kata pand diterjemahkan oleh Soebekti sebagai gadai (jaminan benda bergerak), padahal dalam bahasa Indonesia, istilah gadai bisa mengacu pada benda bergerak maupun tidak bergerak. Begitu juga dengan kata verbintenis (dalam Buku III KUH Perdata), yang diterjemahkan oleh Soebekti sebagai perikatan, oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai persetujuan/perjanjian, dan oleh kalangan akademik UGM sebagai perhutangan.
Sebagai simpulan, hukum dan bahasa hukum Belanda umumnya bersifat abstrak, sebagai dampak dari pengaruh aliran atau mazhab kontinental. Sebaliknya, hukum dan bahasa hukum Indonesia cenderung bersifat konkret, mirip dengan sistem hukum Inggris (common law). Ini sejalan dengan karakteristik bahasa hukum masyarakat Indonesia yang lebih konkret. Misalnya, dalam membedakan antara benda berwujud dan tidak berwujud (bergerak dan tidak bergerak), digunakan istilah “tanah” untuk benda berwujud, dan “bukan tanah” untuk benda tidak berwujud atau bergerak. Dengan demikian, pembenahan terhadap bahasa hukum Indonesia menjadi sangat penting agar mampu mencerminkan nilai, struktur, dan idiom bahasa Indonesia secara utuh dan komunikatif.