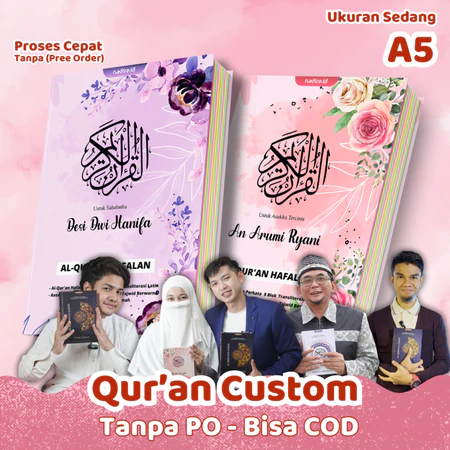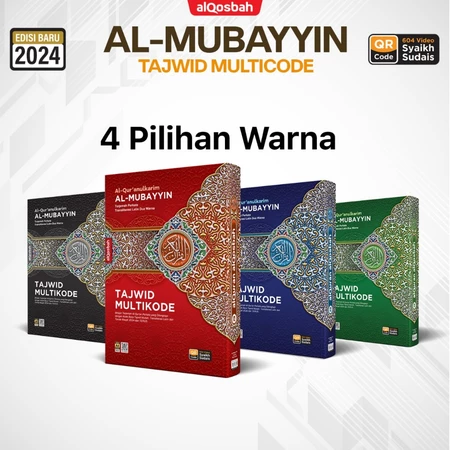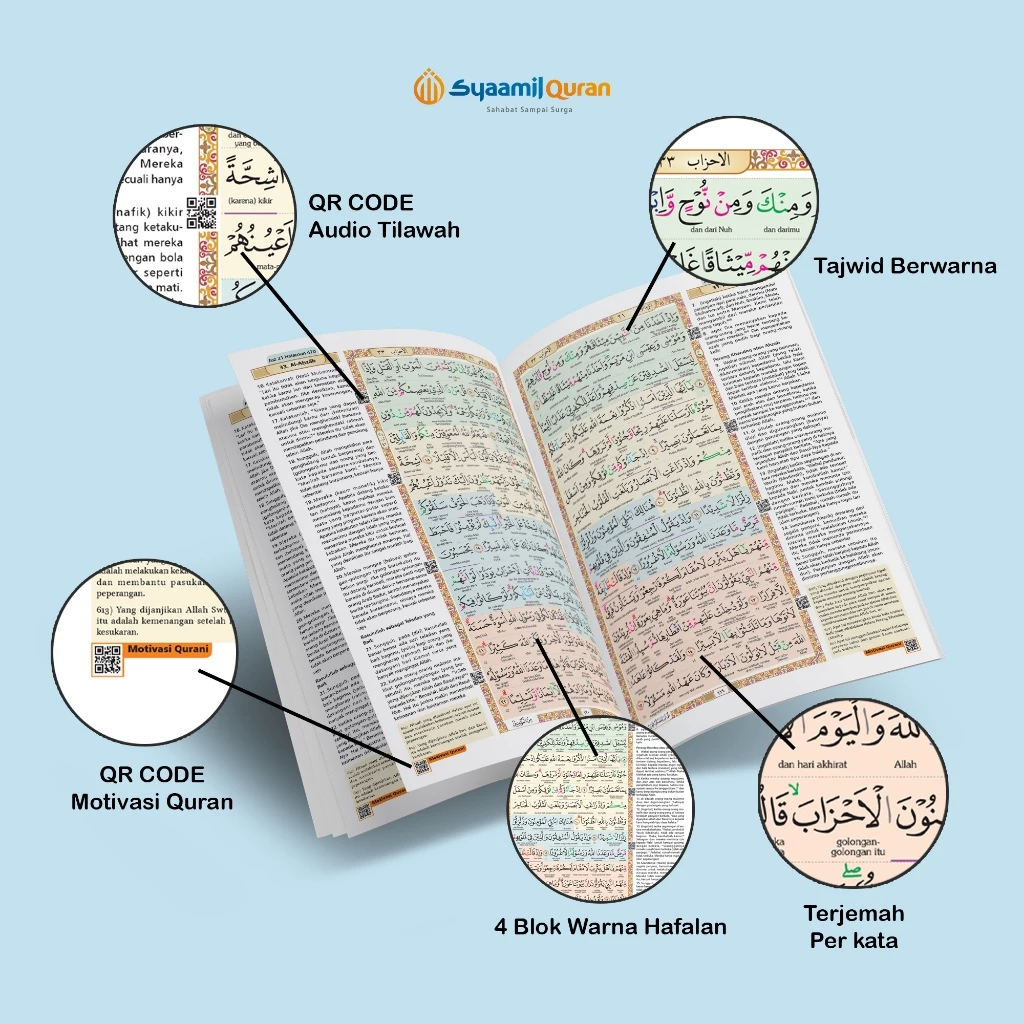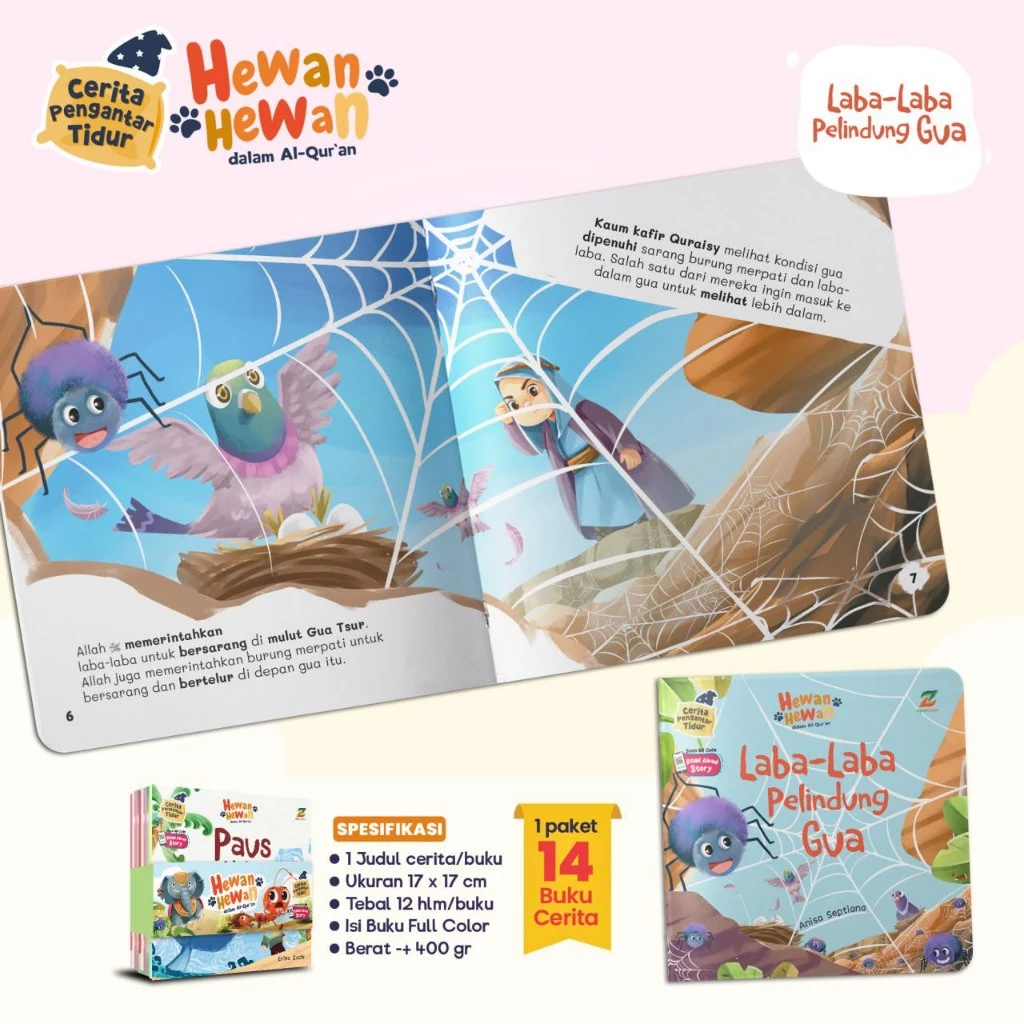Kisah Balik “Menjaga Warisan Leluhur”: Refleksi Budaya dan Hukum Adat
Penulis: H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. (Ketua Peduli Marga Batang Hari Sembilan)
Jendelakita.my.id. - Artikel ini diawali dengan pertanyaan: apakah benar dan mengapa warisan leluhur perlu dijaga? Tentu kita perlu merefleksikan kembali ingatan masa lalu terhadap sikap budaya dan hukum adat dari masa ke masa, termasuk dampak kebijakan publik yang diambil penguasa pada masanya. Minimal, kita dapat menelusurinya sejak zaman kolonial Belanda, masa Orde Lama (awal kemerdekaan), Orde Baru, hingga era Reformasi.
Pada masa kolonial Belanda, khususnya terkait kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap budaya (baca: hukum adat), sikap pemerintah berubah-ubah—kadang menghargai, tetapi kemudian membatasi. Salah satu momen penghargaan kolonial Belanda terhadap hukum adat adalah melalui teori Reception in Complexio yang dipopulerkan oleh dua sarjana Belanda, Prof. Von Keyzer dan Prof. Van de Boss, yang menyatakan bahwa hukum adat suatu masyarakat adat merupakan hasil resepsi keseluruhan dari sistem hukum agama mereka. Dengan teori ini, pemerintah kolonial mengeluarkan aturan bahwa hukum adat diakui keberadaannya untuk mengatur aktivitas sehari-hari. Sebagai contoh, di Sumatera Selatan diberlakukan Simbur Cahaya yang dicetak atas perintah Van den Berg tahun 1852.
Namun, kebijakan tersebut tidak berjalan mulus. Muncullah aturan bahwa “hukum adat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum kolonial” (lihat AB, RR, dan terakhir IS). Menjelang berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda, dikeluarkan dasar pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat yang dikenal sebagai IGO untuk Jawa-Madura dan IGOB untuk luar Jawa-Madura, termasuk Sumatera Selatan (yang menjadi dasar berlakunya sistem marga).
Memasuki masa kemerdekaan, setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, keesokan harinya, 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan dasar berdirinya bangsa dan negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang kemudian diperingati sebagai Hari Konstitusi, dan tahun 2025 ditetapkan sebagai hari libur nasional). Tidak banyak perubahan saat itu, karena seluruh peraturan pemerintah terdahulu (kolonial) tetap diberlakukan melalui Aturan Peralihan UUD 1945, sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan hukum adat sebagaimana tercantum pada Pasal 131 IS ayat 2 sub b junto Pasal 163 IS.
Situasi ini, baik secara teoritis maupun praktis, tidak banyak berubah. Pada masa Orde Baru (1966–1998), pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan terkait hukum adat. Misalnya, Undang-Undang Pokok Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 37 menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (yang salah satunya adalah hukum adat). Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 mengatur bahwa apabila terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing (termasuk hukum adat). Dua ketentuan ini pada prinsipnya memberlakukan hukum adat sepenuhnya.
Namun, keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 justru menghapus kelembagaan masyarakat hukum adat seperti nagari dan marga dari sistem pemerintahan, diganti dengan sistem desa (pola Jawa) yang bersifat sentralistik. Hal ini berdampak pada pola pemerintahan daerah, termasuk di Sumatera Selatan yang sebelumnya menggunakan sistem marga (berdasarkan IGOB). Yang dihapus bukanlah kesatuan masyarakat hukum adat (yang tetap diakui), tetapi lembaga pemerintahannya. Perubahan ini juga memengaruhi interaksi sosial. Dahulu dikenal figur tokoh adat seperti pasirah (lihat Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 142/KPTS/III/1983, butir tiga, yang menegaskan pengakuan masyarakat hukum adat beserta hukum adatnya yang selanjutnya disebut lembaga adat).
Memasuki era Reformasi (1998–sekarang), sistem pemerintahan bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi melalui otonomi daerah yang seluas-luasnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kembali mengakui masyarakat hukum adat sesuai sebutan masing-masing seperti sediakala. Pada saat itu, Sumatera Selatan sebenarnya memiliki peluang untuk mengembalikan eksistensi masyarakat hukum adat, seperti yang dilakukan Sumatera Barat dengan sistem nagari dan wali nagari. Yang diambil seharusnya adalah nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, seperti mengembalikan fungsi tokoh adat (kiyai, jurai tue, dan lainnya), bukan menghidupkan lagi sistem marga berdasarkan IGOB yang bertentangan dengan asas nasionalisme sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 1979.
Pada peringatan Hari Masyarakat Hukum Adat 9 Agustus 2006 di Taman Mini Indonesia Indah, Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidatonya menyatakan akan membuat Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (berita ini dimuat di Republika dan Kompas tanggal 10 Agustus 2006). Namun, hingga artikel ini ditulis, UU tersebut belum juga disahkan.
Secara parsial, memang ada beberapa undang-undang yang menyentuh aspek eksistensi dan perlindungan masyarakat hukum adat. Norma pengakuan ini bermula dari Ketetapan MPR RI tahun 1998, dilanjutkan dengan undang-undang tahun 1999, kemudian diangkat ke dalam UUD NRI 1945 pada tahun 2000 (Perubahan Pasal 18B ayat 2). Perubahan ini membawa pemahaman bahwa negara tidak hanya mengatur wilayah secara administratif, tetapi juga mengakui entitas sosial budaya yang hidup di dalamnya. Sayangnya, pembagian daerah tidak secara eksplisit menjelaskan kedudukan masyarakat hukum adat dalam pemerintahan daerah.
UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyerahkan pengaturan masyarakat hukum adat kepada mekanisme daerah melalui perda dan pengesahan kepala daerah. Namun, hanya sebagian kecil pemerintah daerah yang memahami dan mengimplementasikannya secara aktif, karena ketiadaan pedoman nasional untuk memverifikasi keberadaan masyarakat hukum adat secara proporsional.
Masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki karakteristik hukum adat yang beragam. Ada yang memiliki hukum adat tertulis (tercatat menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, seperti Simbur Cahaya), dan ada pula yang tidak tertulis namun tetap dituturkan, diajarkan, dan ditradisikan dari generasi ke generasi. Pengalaman penulis sebagai praktisi pengelola lembaga hukum adat sejak 1999 menunjukkan bahwa setiap kali mengusulkan pembuatan perda kabupaten/kota, pemerintah daerah selalu beralasan menunggu perda provinsi terlebih dahulu. Padahal, kabupaten/kota memiliki kewenangan langsung untuk menyusunnya sesuai Pasal 18B ayat 2 UUD NRI 1945.
Pasal 18B ayat 2 memuat kewajiban aktif pemerintah pusat dan daerah untuk mengonkretnya perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat dalam kerangka otonomi daerah. Namun, realisasinya masih lemah karena minimnya komitmen politik, absennya regulasi khusus, dan keterbatasan pengaturan operasional. Diperlukan langkah konstitusional dan legislasi lanjutan untuk memastikan otonomi daerah juga menjadi ruang penguatan identitas dan hak masyarakat hukum adat.
Pasal 2 KUHP 2023 menegaskan bahwa kedudukan hukum adat tidak lagi berada di luar sistem hukum negara, melainkan secara eksplisit diakui sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara hukum. Namun, pengakuan ini akan sia-sia tanpa reformasi substansial, khususnya pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat (yang sudah masuk Prolegnas DPR RI) menjadi undang-undang. Inilah bentuk nyata “Menjaga Warisan Leluhur.”