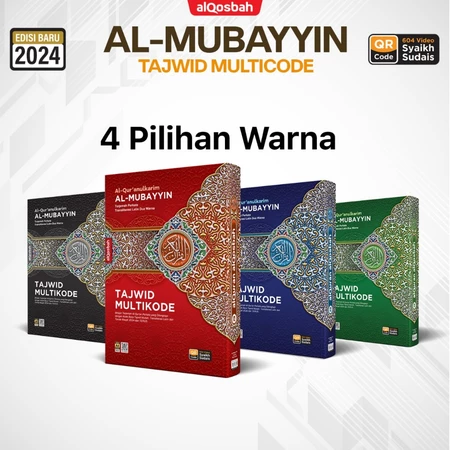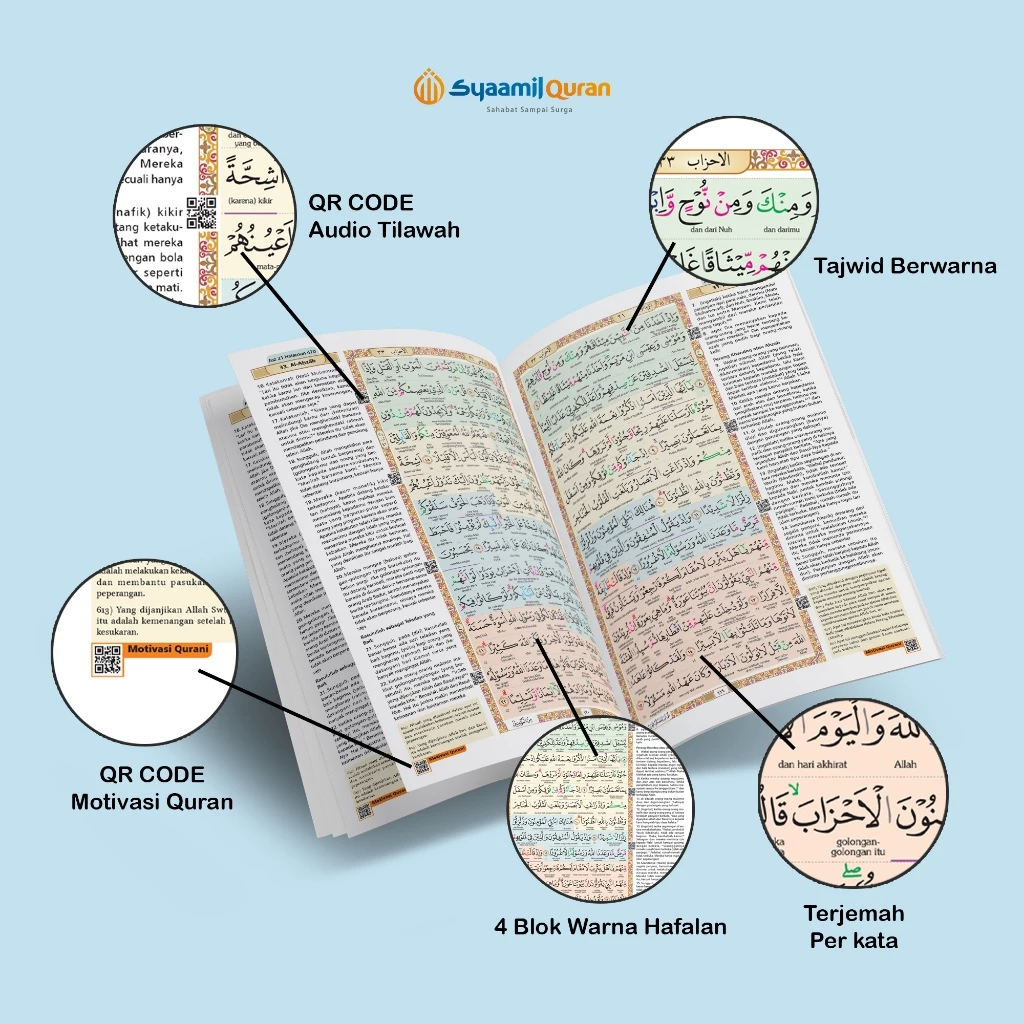Dibalik Ulir Padi : Jurnalisme dari Desa Sukamaju
Penulis : Asrul Satriadi
Mahasiswa Semester V Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) STAI BS Kota Lubuklinggau
A. Pendahuluan
Embun pagi menyapa sawah Sukamaju ketika Pak Saman, petani berusia 58 tahun, menatap hamparan padi. “Selama matahari masih terbit, kami akan menanam,” katanya. Sawah baginya bukan sekadar sumber hidup, melainkan warisan.
Aktivitas desa dimulai sejak pagi: gemericik air, kokok ayam, dan derit motor membawa pupuk. Bu Minah, 47 tahun, menyiangi gulma sambil mengeluhkan harga pupuk yang melonjak dari Rp120 ribu menjadi Rp250 ribu per sak. Biaya produksi tinggi, hasil panen rendah, dan ketergantungan pada tengkulak menjadi masalah klasik.
Data Dinas Pertanian menunjukkan lahan sawah menyusut dari 320 hektar (2010) menjadi 250 hektar. Alih fungsi lahan mempersempit ruang hidup petani. Meski begitu, tradisi gotong royong membersihkan irigasi dan anak-anak yang membantu menanam padi masih menjadi perekat sosial. Sawah tetap menjadi simbol ketahanan desa.
B. Tantangan di Balik Kuning Padi
Harga gabah fluktuatif. Saat panen raya, harga bisa jatuh hingga Rp4.000/kg. Petani terpaksa menjual ke tengkulak karena tidak punya akses pasar. Data BPS menunjukkan selisih besar antara harga gabah di petani dan harga beras di pasar.
Selain harga, biaya produksi terus naik. Pupuk subsidi sering langka, membuat petani antre panjang di gudang desa. Joni, petani muda, mengeluhkan sistem kuota yang tidak merata. Irigasi rusak dan cuaca tak menentu menambah beban.
Generasi muda menghadapi dilema. Sebagian bertahan seperti Joni yang mencoba inovasi teknologi, namun banyak memilih merantau ke kota. Sawah dianggap berat dengan hasil kecil. Di balik hamparan hijau, tersimpan cerita tentang harga tak menentu, pupuk sulit diakses, irigasi rusak, dan generasi yang mulai berpaling.
C. Kebijakan dan Realitas
Di balai desa, papan pengumuman pupuk subsidi terpajang dengan tinta pudar. Kuota terbatas membuat sebagian petani harus membeli pupuk nonsubsidi dua kali lipat lebih mahal.
Irigasi menjadi isu krusial. Pemerintah kabupaten menjanjikan perbaikan saluran rusak, namun proyek tak kunjung berjalan. Petani bergotong royong memperbaiki seadanya, meski mudah jebol saat hujan deras.
Bulog seharusnya menjadi penyangga harga gabah, tetapi hanya membeli dengan standar tertentu. Banyak gabah ditolak, sehingga petani tetap bergantung pada tengkulak. Jurang antara kebijakan di atas kertas dan realitas lapangan semakin nyata. “Kami tidak butuh janji, kami butuh sawah yang bisa ditanami,” tegas Pak Saman.
D. Penutup
Sawah Sukamaju adalah ruang hidup, perjuangan, dan harapan. Dari embun pagi hingga antrean pupuk, semua menggambarkan denyut pertanian desa. Kebijakan pemerintah hadir di atas kertas, tetapi di lapangan petani bertahan dengan keyakinan bahwa sawah adalah warisan.
Generasi muda memberi secercah harapan dengan ide baru, meski tantangan besar tetap ada: bagaimana menjadikan pertanian menarik dan berdaya saing. Sawah adalah cermin bangsa—memantulkan wajah petani, kebijakan, dan ketergantungan kita pada nasi. Menjaga sawah berarti menjaga sejarah dan kehidupan.
Pak Saman menutup dengan kalimat sederhana:
“Selama matahari masih terbit, kami akan menanam. Tapi kami berharap, suatu hari nanti, perjuangan kami tidak lagi berjalan sendiri.”
Suara Penulis :
Sebagai jurnalis, saya datang dengan niat mendengar dan mencatat. Dari Pak Saman, Bu Minah, dan Joni, saya belajar bahwa pertanian adalah perlawanan sunyi terhadap ketidakpastian.
Saya melihat harapan dalam embun pagi, kegelisahan dalam antrean pupuk, dan senyum saat bulir padi menguning. Menulis tentang petani berarti menulis tentang ketahanan bangsa. Nasi yang kita makan adalah hasil tangan-tangan yang jarang terlihat.
Jurnalisme harus hadir di sawah, di ladang, di ruang-ruang yang sering terpinggirkan. Karena di sanalah cerita bangsa sesungguhnya berakar.