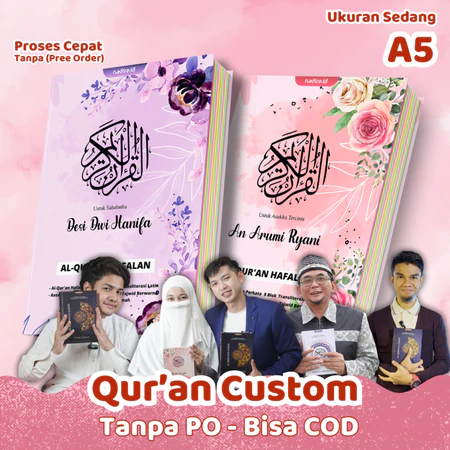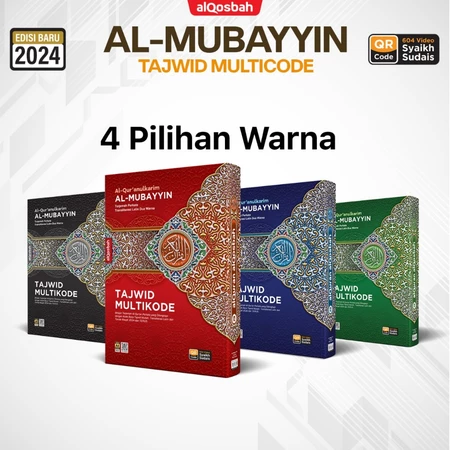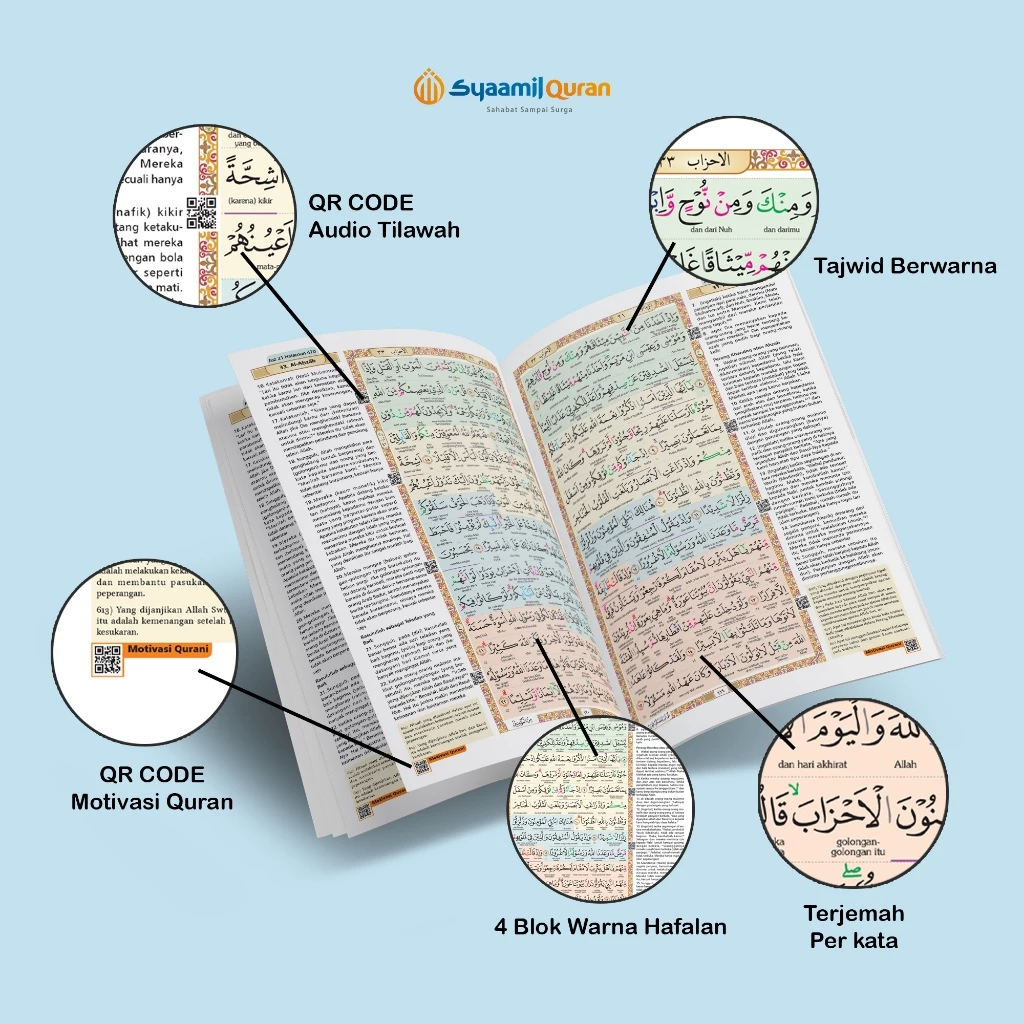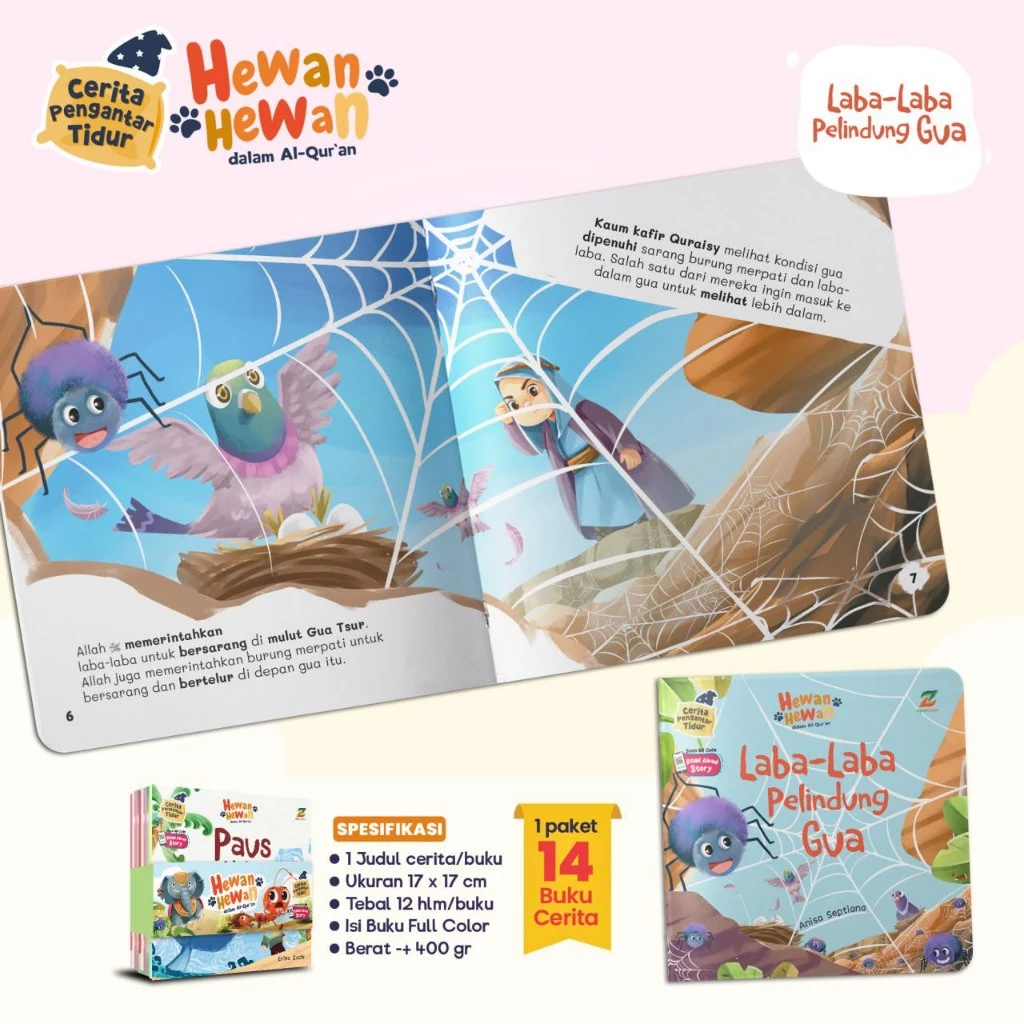Realitas Sosial Masyarakat Hukum Adat
Penulis: H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. (Ketua Peduli Marga Batang Hari Sembilan)
Jendelakita.my.id. - Secara empirik, realitas sosial-budaya yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat cukup beragam serta memperlihatkan dinamika perkembangan yang bervariasi. Secara garis besar, kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat tipologi.
Pertama, kelompok masyarakat lokal yang masih kukuh berpegang pada prinsip pertapa bumi, yakni sama sekali tidak mengubah cara hidup mereka, seperti adat bertani, berpakaian, pola konsumsi, dan sebagainya. Mereka tetap eksis tanpa berhubungan dengan pihak luar dan memilih menjaga kelestarian sumber daya serta lingkungan dengan kearifan lokal tradisional mereka. Contoh kelompok ini dapat dijumpai pada komunitas To Kajang (Kajang Dalam) di Bulukumba dan Kanekes di Banten.
Kedua, kelompok masyarakat lokal yang masih ketat dalam memelihara serta menerapkan adat istiadat, tetapi tetap membuka ruang interaksi “komersial” dengan pihak luar. Komunitas semacam ini umumnya dapat dijumpai pada masyarakat Kasepuhan Banten Kidul dan Suku Naga, yang keduanya berada di Jawa Barat.
Ketiga, kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup bergantung pada alam (seperti hutan, sungai, gunung, laut, dan lainnya) dan mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam yang unik. Namun, mereka tidak mengembangkan adat yang ketat dalam hal perumahan atau pemilihan jenis tanaman, sebagaimana kelompok pertama dan kedua. Komunitas yang termasuk dalam tipologi ini antara lain adalah Dayak Penan di Kalimantan, Pakava dan Lindu di Sulawesi Tengah, Dani dan Deposoro di Papua Barat, Krui di Lampung, serta Haruku di Maluku.
Keempat, kelompok masyarakat hukum adat yang telah tercabut dari tatanan pengelolaan sumber daya alam “asli” akibat penjajahan yang berlangsung selama ratusan tahun. Kelompok ini termasuk masyarakat Melayu Deli di Sumatera dan Betawi di wilayah Jabodetabek.
Hingga hari ini, perkembangan masyarakat hukum adat semakin dinamis dan beragam. Oleh karena itu, mustahil untuk melakukan penyeragaman. Terdapat tarik-menarik antara kepentingan standardisasi nasional dengan keragaman lokal. Agar perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat terwujud sepenuhnya, maka Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat seharusnya lebih dahulu disahkan sebelum lahirnya Undang-Undang tentang Pembentukan Desa. Hal ini penting, karena Undang-Undang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat merupakan amanat konstitusi.
Hukum Adat sebagai Living Law
Untuk merefleksikan pemahaman kita, penting kiranya untuk memahami makna hukum adat, yang disebut juga sebagai living law (hukum yang hidup dalam masyarakat). Hukum adat merupakan adat yang bersifat normatif, yaitu adat yang mengandung kekuatan hukum. Menurut Ter Haar (1937), hukum adat adalah “adat yang diberi sanksi oleh masyarakat.”
Keberadaan hukum adat dihargai, dihormati, dan dipatuhi oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap norma-norma hukum adat akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai aturan adat yang berlaku. Dalam perkembangannya, masyarakat hukum adat dan norma-norma hukum adat yang berlaku di dalamnya bersifat dinamis, seiring dengan perkembangan zaman.
Pepatah lama yang menyatakan bahwa "adat tidak lekang karena panas, dan tidak lapuk karena hujan", dalam kenyataannya mengalami perubahan. Jumlah masyarakat hukum adat yang benar-benar asli dan belum terpengaruh oleh dunia luar semakin berkurang. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta masuknya sistem pemerintahan hingga ke daerah terpencil telah membuka isolasi yang selama ini melindungi masyarakat adat. Secara perlahan, nilai-nilai dan norma baru mulai bersentuhan dengan kehidupan mereka.
Bahkan jauh sebelum era modern, ajaran agama-agama besar dunia juga telah membawa perubahan dalam masyarakat hukum adat. Proses ini umumnya berlangsung damai dan persuasif. Norma-norma hukum adat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama secara perlahan menemukan titik konvergensi. Hal ini sesuai dengan gagasan Ki Hadjar Dewantara mengenai Tri Kon: kontinuitas, konvergensi, dan konsentrisitas.
Adat dan Syariat dalam Perspektif Minangkabau dan Melayu
Di tanah Minangkabau dan masyarakat Melayu pada umumnya, terdapat pepatah adat yang berbunyi:
“Adat bersendi syara’, syara’ bersendi Kitabullah.”
Pepatah tersebut bermakna bahwa adat haruslah berdasarkan pada syariat agama, dan syariat agama itu bersumber dari Kitabullah, yaitu Al-Qur’an.