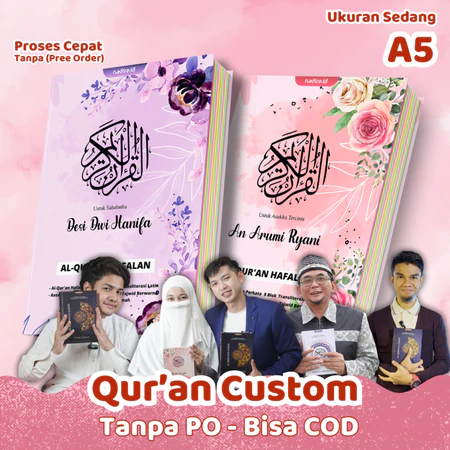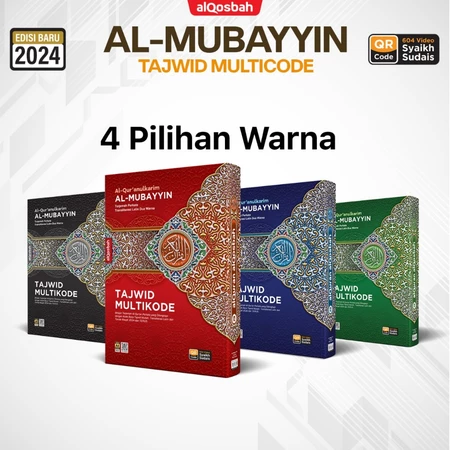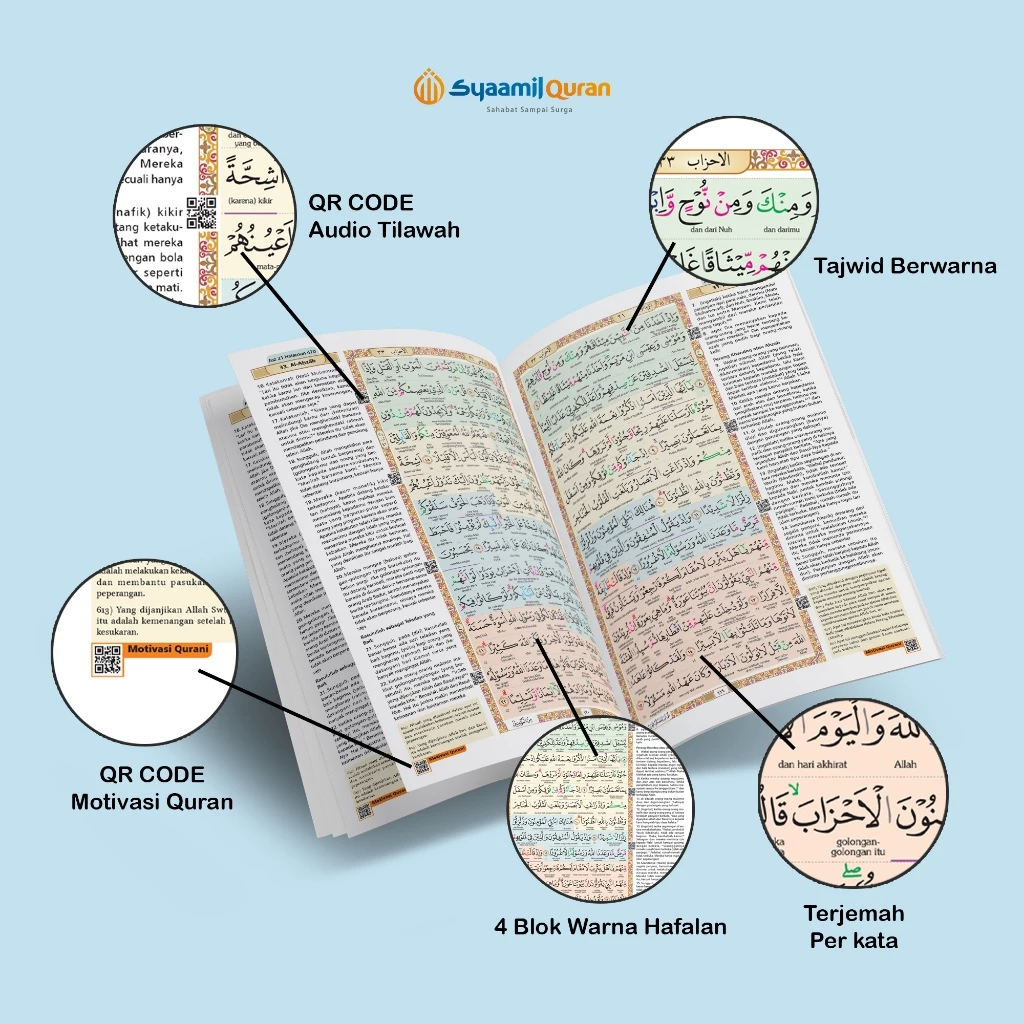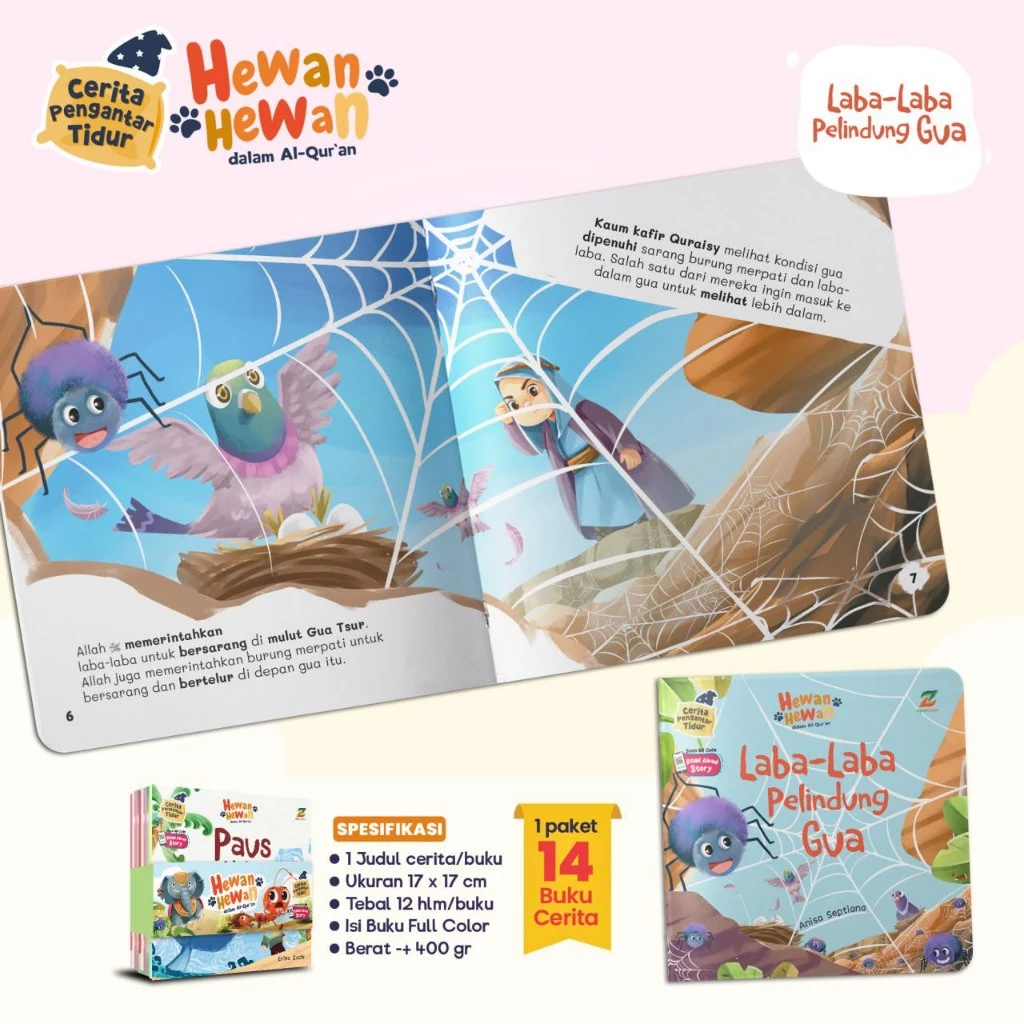Bahasa Hukum Adat dalam Kancah Hukum Nasional
Jendelakita.my.id. - Yang dimaksud dengan hukum adat dalam tulisan ini adalah hukum yang tidak tertulis dalam bentuk produk perundang-undangan. Oleh karena itu, kita tidak menemukan rumusan kaidah-kaidahnya dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis. Namun, terkadang hukum adat dirumuskan oleh yurisprudensi, peneliti, penulis buku, dosen, dan sebagainya dalam kalimat-kalimat yang tersusun baik. Dalam bentuk demikian, hukum adat tersebut telah “diangkat” menjadi hukum yang tertulis, meskipun secara esensial ia tetap merupakan hukum tidak tertulis—kecuali pada suatu waktu diangkat menjadi hukum tertulis dalam bentuk perundang-undangan.
Prof. Iman Sudiyat, S.H., Guru Besar Hukum Adat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang juga merupakan pembimbing tesis penulis, menyatakan bahwa hukum nasional harus memenuhi syarat materiel dan formil, yaitu syarat formil harus dibentuk oleh pembuat undang-undang (DPR bersama Presiden).
Dalam kaitannya dengan pernyataan tersebut, dapat dimaknai bahwa hukum adat (hukum tidak tertulis) dapat ditemukan dalam yurisprudensi, tulisan para sarjana, dan dokumen lainnya. Salah satunya termasuk kompilasi seperti Simbur Cahaya. Simbur Cahaya bukanlah sebuah kitab undang-undang dalam arti sesungguhnya, walaupun dalam pengantar De Resident Belanda (terbitan 1852) dan versi Pasirah Bond tahun 1927, istilah tersebut dimaknai sebagai aturan-aturan adat istiadat yang diberlakukan sebagai undang-undang, namun tidak dapat dimaknai sebagai wet (hukum formal tertulis Belanda).
Selain termuat dalam yurisprudensi dan tulisan para sarjana (doktrin dan fatwa), hukum adat juga dapat ditemukan dalam simbol-simbol budaya: disampaikan secara lisan, dimuarakan dalam satu atau beberapa kata yang menjadi nama lembaga, dituangkan dalam perumpamaan, pepatah, atau dikonkretkan dalam tanda-tanda seperti simbol tanjak (tutup kepala).
Sebagai contoh, istilah “harta pusako” di Minangkabau menyimpan seperangkat makna norma adat. Misalnya, lembaga harta pusako dapat dibandingkan dengan hak ulayat. Apabila intensitas hak warga dalam persekutuan hukum melengkungkan hak kolektif persekutuan, maka hak anggota kaum dapat melebihi hak kaum itu sendiri. Semakin kuat hak anggota, semakin lemah hak kaum. Dalam konteks ini berlaku pepatah: “kabau tagak, kubang tingga” (kerbau tegak, kubangan ditinggal). Artinya, jika satu kerbau sudah berdiri dan meninggalkan kubangannya, maka kerbau lain dapat memanfaatkan kubangan yang ditinggalkan itu. Jika suatu tanah pusako tidak lagi digunakan oleh satu pihak, maka mamak (paman adat) dari kaum dapat menyerahkan tanah tersebut kepada anggota lain dalam kaum. Pada asasnya, tanah pusako tidak boleh digadaikan, kecuali dalam keadaan tertentu seperti untuk memperbaiki rumah gadang yang bocor.
Dalam lembaga “pauseang” (Batak), terkandung sejumlah kaidah hukum adat mengenai siapa yang memberikan dan menerima pauseang, kapan pauseang diberikan, apa tujuannya, dan apakah tanah pauseang dapat dijual atau digadaikan. Arti anak angkat dalam masyarakat Melayu juga tidak serupa dengan lembaga yang sama namanya di masyarakat Jawa Tengah. Di sini terlihat bahwa pepatah dan pribahasa selalu mengandung nilai hukum. Misalnya, pepatah “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung” sepadan dengan asas lex loci dalam hukum perdata internasional. Pepatah lain, “Hewan dipegang talinya, manusia dipegang janjinya” mencerminkan makna serupa dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Sementara pepatah “Kain dipakai usang, adat dipakai baru” menunjukkan bahwa adat istiadat terus berkembang, mengalami penyempurnaan, bahkan mengandung benih-benih perubahan seiring tumbuhnya kebiasaan dalam kehidupan keluarga batin.
Perubahan sosial dalam masyarakat Minangkabau juga mengubah praktik hukum adat, seperti berkurangnya perhatian kepada kemenakan (keponakan) akibat meningkatnya perhatian terhadap anak kandung. Maka muncullah pepatah “Anak dipangku, kemenakan dibimbing.” Dari pepatah ini lahir norma hukum adat bahwa “harta pencaharian dikuasai anak,” sebagaimana tercermin dalam beberapa yurisprudensi di Pengadilan Negeri di Sumatera Barat maupun putusan Mahkamah Agung.
Hal ini sejalan dengan pemikiran Prof. Dr. H. Hazairin, S.H. dalam bukunya Hukum Kewarisan Bilateral, serta pemikiran Prof. Dr. Hamka dalam bukunya Adat Minangkabau Mengalami Revolusi.