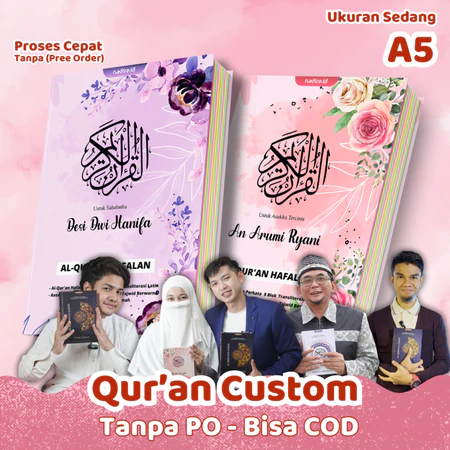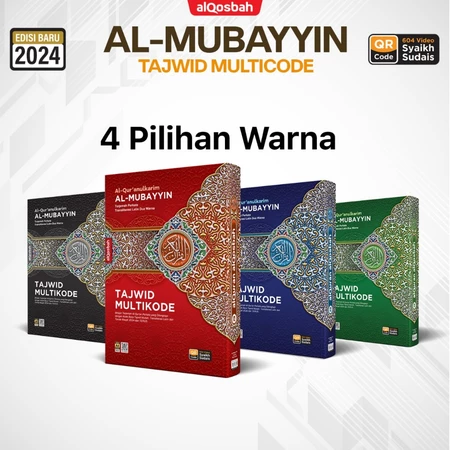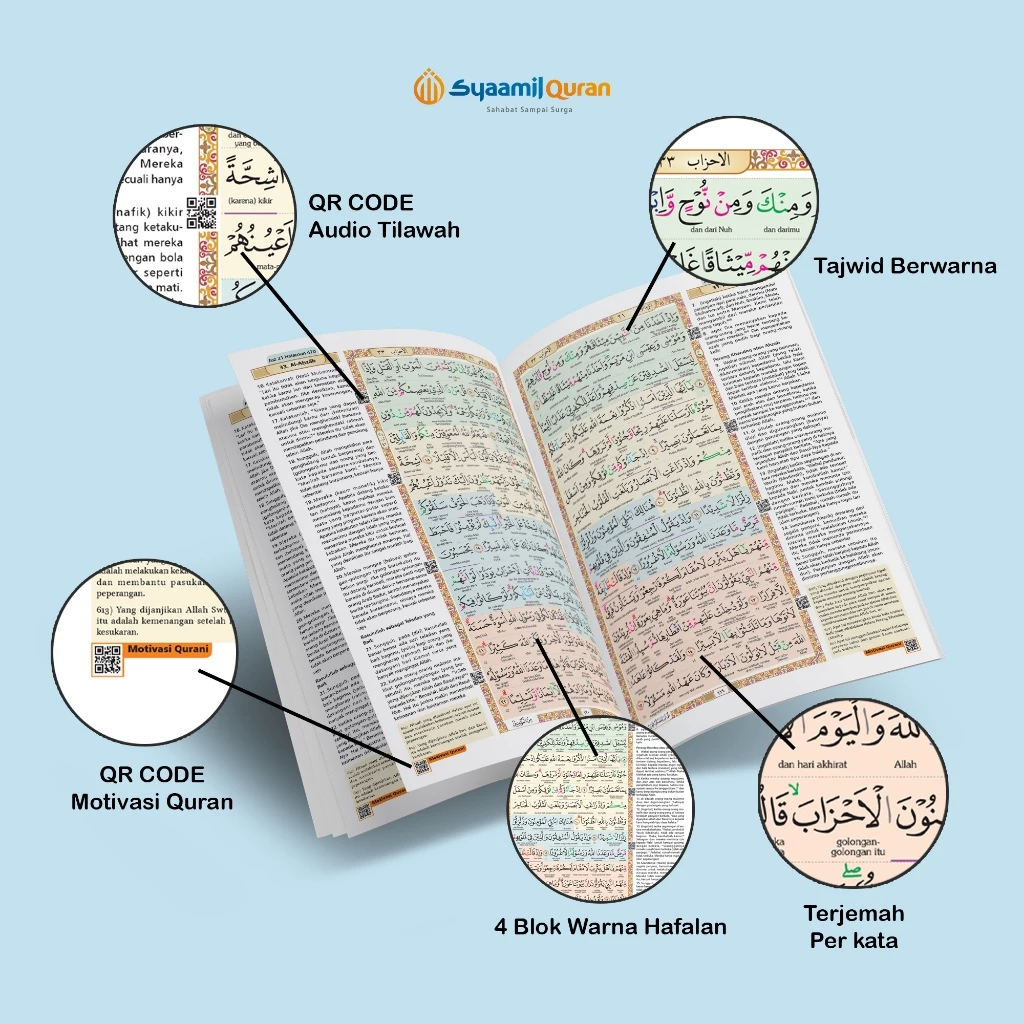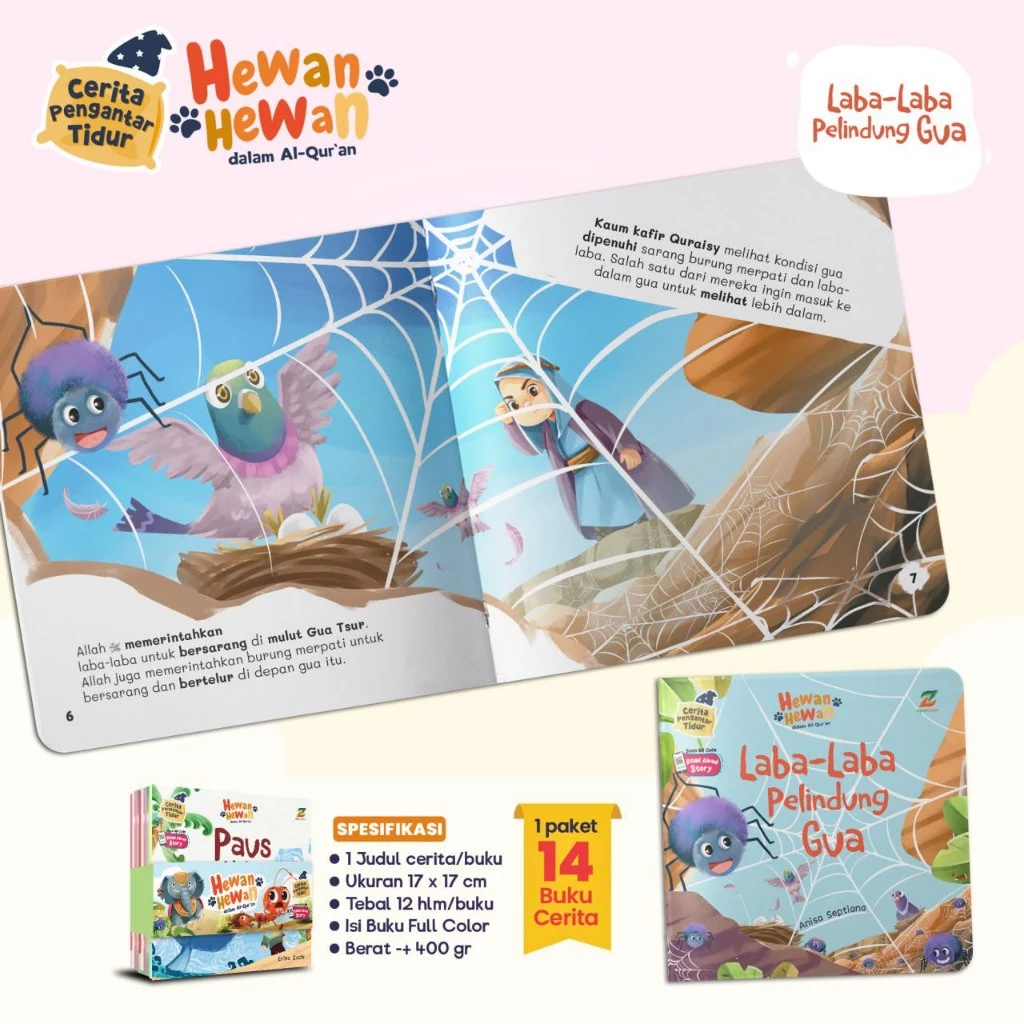Sikap Dasar Pendiri Bangsa Terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Tindaklanjutnya
Tulisan Oleh: H. Albar Sentosa Subari*)
Jendelakita.my.id - Dalam konteks historis sesungguhnya kita amat beruntung, karena perancang UUD 45 --- Prof. Mr. Dr. R. Soepomo -- adalah seorang pakar hukum adat, yang benar benar mengetahui posisi masyarakat hukum adat di Indonesia, dan sehubungan dengan itu mencantumkan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat (volksgemeenschappen) dalam rancangan konstitusi yang sedang disusun nya.
Sudah barang tentu sekarang kita dapat menyayangkan bahwa pengakuan tersebut tidak tercantum secara lugas dalam dictum Undang Undang Dasar 1945, tetapi hanya dalam penjelasan Pasal 18 (Pada angka II penjelasan pasal 18 ; Dalam teritorial negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelbesturende Landschappen dan volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai darah itu akan mengingat hak hak asal usul daerah itu).
Namun, walaupun hanya tercantum dalam penjelasan Pasal 18 UUD 45, sikap para pendiri negara tersebut merupakan " original inten" yang harus dirujuk dalam melakukan tafsiran historis (historische interpretatie) terhadap norma positif yang terkait dengan eksistensi dan hak hak tradisional masyarakat hukum adat ini, paling sedikit selama kita masih menggunakan UUD 45.
Ada suatu kendala konseptual yang sekarang kita sadari amat menghambat upaya untuk sistematik melanjutkan original intent para pendiri negara tersebut ke dalam kebijakan negara dan peraturan perundang-undangan nasional. Kendala konseptual tersebut adalah tidak-- kurang -- berkembangnya pengetahuan kita terhadap perkembangan masyarakat hukum adat ini. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pada dasarnya pengetahuan kita sekarang ini tidak lah lebih maju dari pengetahuan yang kita warisi dari literatur Adat Recht yang diwariskan oleh Cornelis Van Vollenhoven dan atau Ter Haar Bzn. Sementara itu masyarakat hukum adat itu sendiri tumbuh dan berkembang, bahkan tidak mustahil secara teoretikal juga menciut dan menghilang karena lenyap nya ciri ciri khas sebagai suatu masyarakat hukum adat.
Bersama dengan itu, secara perlahan lahan dan tanpa didukung oleh teori yang memadai, telah tumbuh perhatian terhadap etnik atau suku bangsa, sebagai suatu entitas antropologis yang lebih besar. Pada awalnya, perhatian terhadap masalah ini terbatas pada artian simbolik belaka, dalam hubungannya dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang sejak tahun 1951 tercantum dalam Lambang negara. Namun secara perlahan lahan, eksistensi etnik dalam bangsa yang bermasyarakat majemuk ini mempunyai dimensi politik.
Secara teoretikal dapat dipertanyakan, apakah etnik atau suku (1.072 etnik di Indonesia). tersebut juga memperoleh perlindungan konstitusional yang sama seperti halnya dengan masyarakat hukum adat.
Dalam pasal pasal Undang Undang Dasar 45 sama sekali tidak terdapat istilah etnik atau suku bangsa ini (lihat makalah Dr. Saafroedin Bahar -- ketua Dewan Pakar Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat (Seknas MHA) sejak 2007) dan Prof. Dr. Ruswiati Suryasaputra, MS (Komisioner Komnas HAM 1995-2007).
Hanya secara tersirat hal itu bisa disimpulkan dari kalimat yang tercantum dalam Pasal 36 A Undang Undang Dasar 45, yang mengatakan; lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sudah merupakan kelaziman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa istilah Bhinneka Tunggal Ika terkait dengan kemajemukan masyarakat Indonesia dari segi ras, Entik dan agama.
Berbeda dengan belum jelasnya posisi yuridis dari etnik atau suku bangsa, sejak tahun 2001 pembentuk undang-undang secara eksplisit mengakui ras dalam hal ini Rasulullah Papua, dalam Undang Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua.
Melalui penafsiran sistematis rasanya tidak akan terlalu salah jika disimpulkan bahwa negara juga mengakui ras rasnya, seperti ras Melayu, dengan segala bentuk varian nya, tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Sudah barang tentu bisa dipersoalkan bagaimana kah hubungan antara masyarakat hukum adat, etnik, dan ras ini, khususnya dalam hubungan dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersifat kolektif, sesuai dengan berbagai instrumen hukum internasional hak asasi manusia. Untuk itu Komnas HAM melakukan pengkajian dan menyimpulkan adanya hubungan konseptual antara ketiga komunitas primordial ini yang pada dasarnya adalah masyarakat hukum adat adalah bagian dari suatu etnik, sedangkan etik adalah bagian dari ras.
The Republic of Indonesia 2006, Indigenous Peoples; The Structurel Relationship among Tribal Groups, Nations and the State, From A Human Rights Perspective The Indonesian Nationale Commissen of Human Rights, Jakarta (Idem).***
*) Penulis adalah Ketua Koordinator Jejaring Panca Mandala Sriwijaya Sumatera Selatan