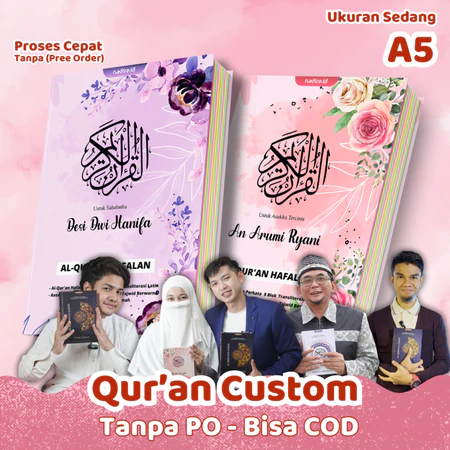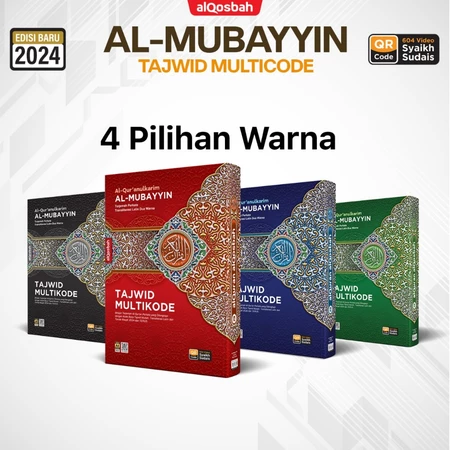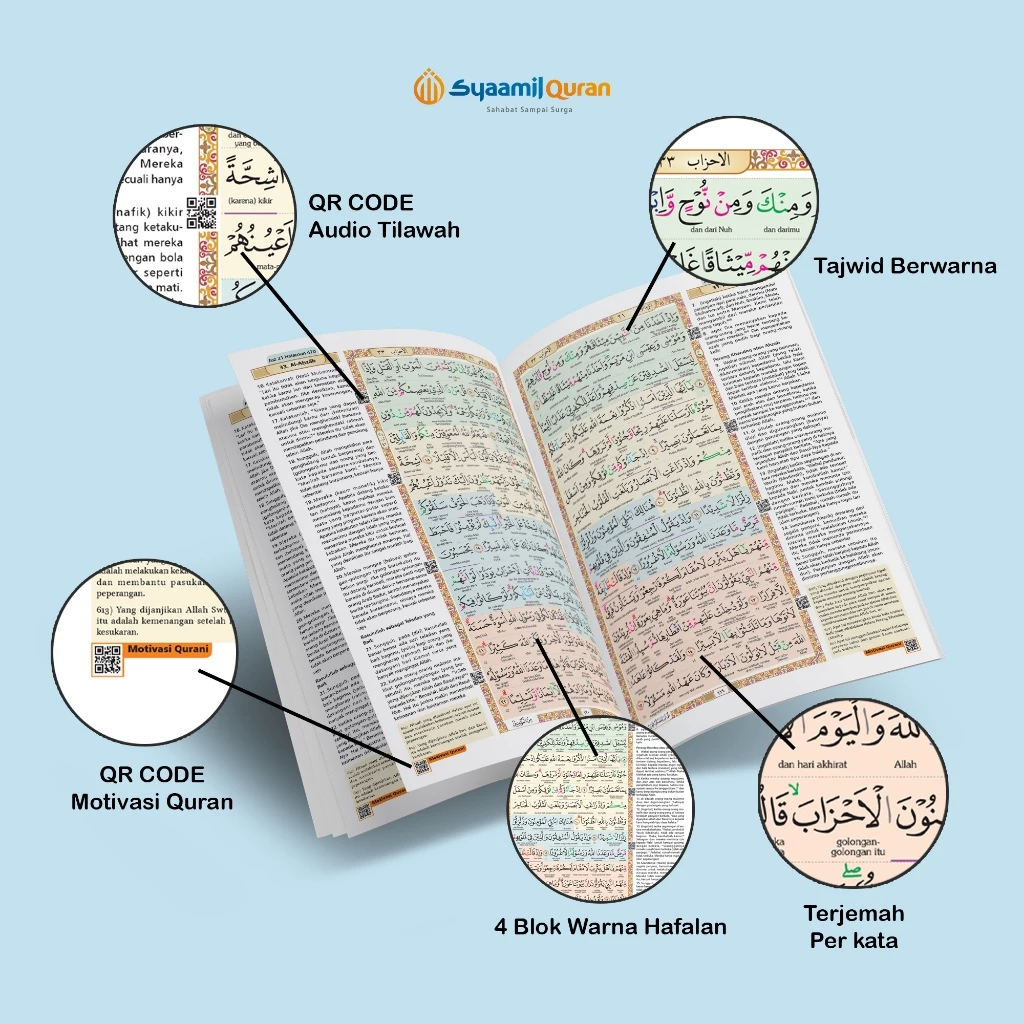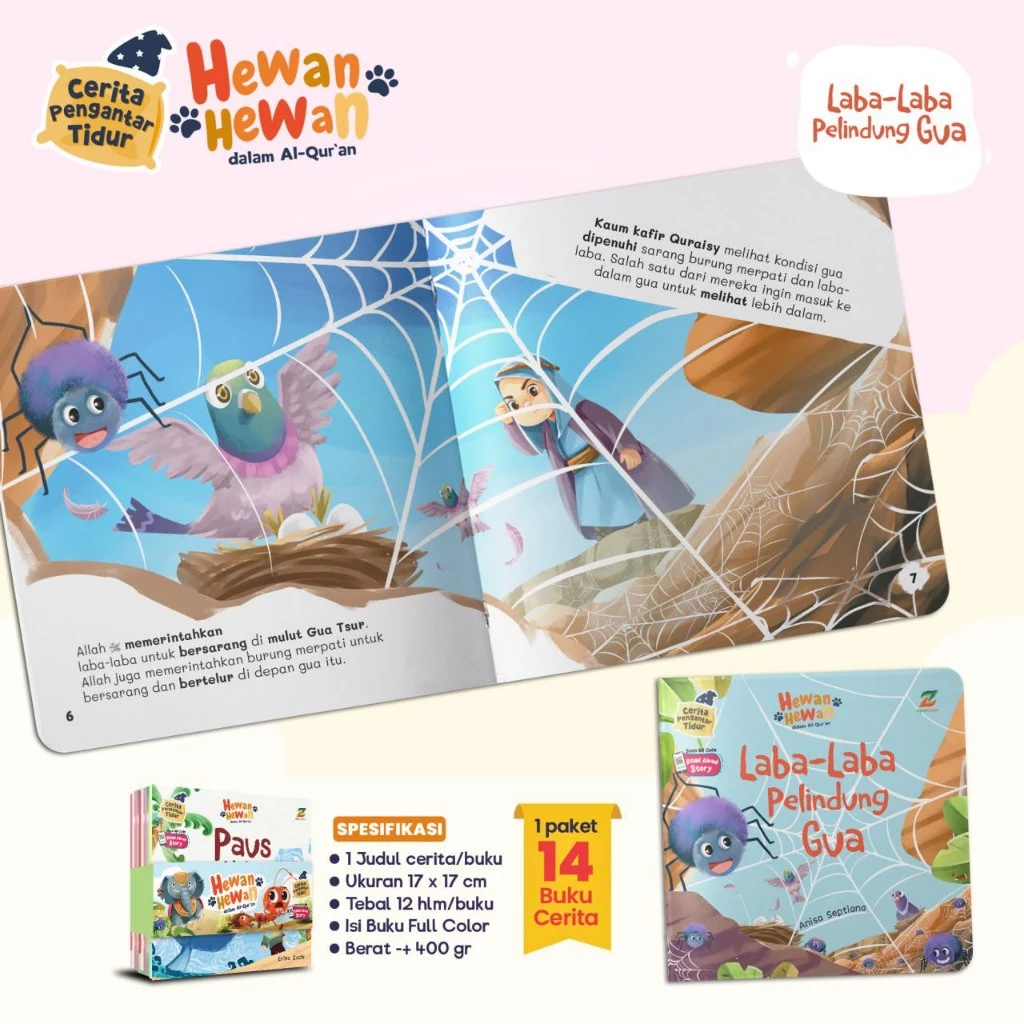Era Reformasi; Periode Sensitif
Opini Oleh: Albar Sentosa Subari*)
JENDELAKITA.MY.ID - Sejak kelahirannya era- reformasi, barang
kali, merupakan periode yang paling sensitif terhadap eksistensi Pancasila.
Fase keterbukaan
yang melampaui batas kebutuhan itu, ternyata cenderung melahirkan eforia yang
tidak produktif dalam memasuki demokrasi subtansial.
Sektarian ideologis
yang di masa lalu terjepit dalam mekanisme struktur kekuasaan otoritarian, kini
muncul dalam semangat kesadaran baru dalam bentuk religiusitas yang ekslusif
dan intoleran.
Betapapun penerapan
rumusan “Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekular" merupakan
jalan tengah yang paling historis, eleborasi empiris dari jalan tengah ini
cenderung mengabaikan perlindungan terhadap kelompok tertentu.
Dalam memecahkan
masalah sengketa hak hak "kepercayaan", misalnya posisi negara
cenderung bertindak sebagai aparatur - keyakinan yang melampaui batas batas
kewenangannya.
Sementara dari
sekalian gejala yang penting merisaukan dalam jangka panjang, khususnya dalam
kaitannya relasi agama dan Pancasila adalah, semakin menyusutnya pemahaman
kebutuhan ideologi nasional sebagai payung " kehendak bersama".
Pancasila secara
berangsur angsur telah mengalami penyusutan peran sebagai guidence tindakan
bernegara dan berbangsa.
Padahal keduanya (agama
dan Pancasila) sebenarnya bisa saling mengisi dan bekerjasama dalam memperkuat
moralitas bangsa, tanpa harus memperebutkan arena yang garis batasnya sengat
jelas.
Pancasila tidak
memiliki jangkauan untuk memberikan penjelasan kepada hal-hal yang bersifat
beyond reality atau segala sesuatu yang bersifat sakral. Jadi sebagai ideologi,
Pancasila bersifat profan. Sebaliknya agama memiliki keterbatasan scope untuk
dijadikan landasan etika universal, yang bisa mempertemukan kehendak semua
agama, yang kosmologinya memang berbeda beda.
Pancasila
membutuhkan agama sebagai sponsor utama dalam mendorong lahirnya etika
berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada kesalehan sosial yang dipetik dari
ajaran agama.
Sebaliknya agama
membutuhkan Pancasila dalam mempertemukan nilai nilai universal yang ada dalam
seluruh ajaran agamanya, seperti: keadilan, kesamaan, kemanusiaan dan
sebagainya.
Simbiose mutualistik
ini sebenarnya bisa terjadi, jika keduanya menyadari posisinya masing masing.
Pertanyaannya mengapa Pancasila dan Agama secara semipermanent telah mengalami
ketegangan.
Peringatan hari kelahiran Pancasila 1 Juni 2008 yang
dilakukan di Monas, yang telah dinodai oleh kekerasan kolektif yang bersumbu
pada egoisme kolektif yang menumpang pada semangat keagamaan, merupakan contoh
betapa rentannya pemahaman kebangsaan kita (Lihat Anas Said Mahfud, dalam
Soenarto Soedarno, 2009: 168).
Rasanya belum pernah terjadi dimana polarisasi pemahaman
Indonesia sebagai bangsa yang plural, telah mendapatkan tantangan yang paling
merisaukan melebihi saat ini.
Semuanya ini harus menjadi pelajaran yang berarti bahwa
apapun perbedaan keyakinan yang kita miliki, kekerasan bukanlah jalan
keluarnya.
Tukar- gagasan dan dialog yang terus menerus dengan saling
menghargai perbedaan keyakinan harus menjadi landasan utama.
Sekiranya kehendak bersama tetap tidak berhasil dirumuskan,
maka semangat berbeda beda tetapi tetap satu (Bhinneka Tunggal Ika), harus
tetap menjadi lem perekat untuk berbangsa dan bernegara.
Keyakinan tidak dapat dipaksakan. Dakwah harus dilakukan
secara persuasif dan bijaksana. Ketegangan Agama dan Pancasila hanya bisa
direduksi jika para pendukungnya tidak saling memaksa kehendak serta menyadari
fungsi dan limitasinya masing masing. ***
*) Penulis adalah Ketua
Koordinator Jejaring Panca Mandala Sriwijaya Sumatera Selatan