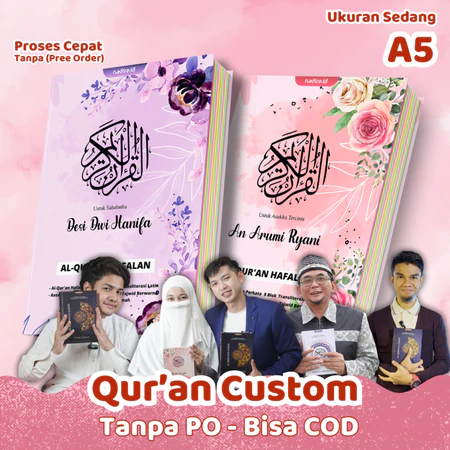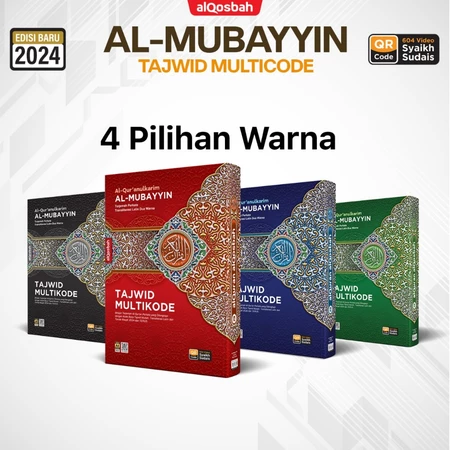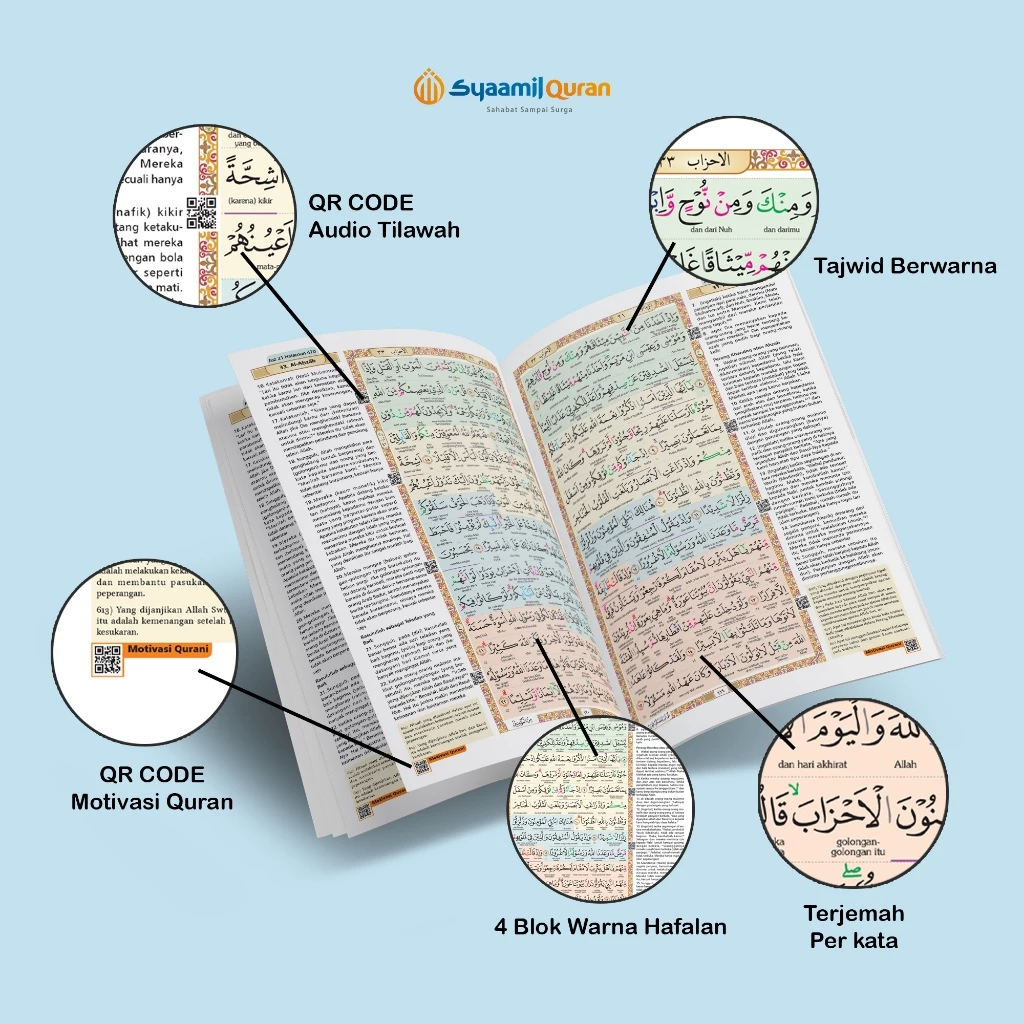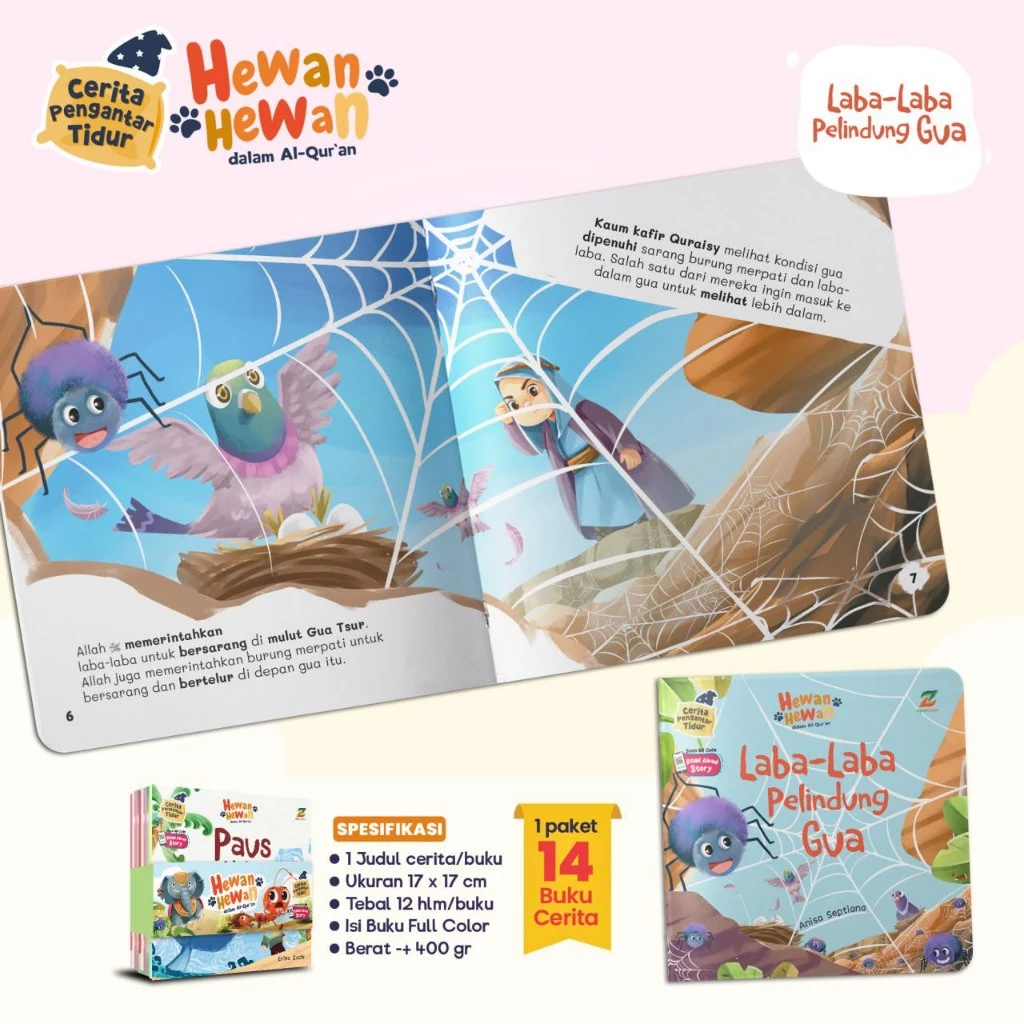Resume Buku "Sosiologi Kehidupan Sehari-hari" karya Wahyu Budi Nugroho, sosiolog Universitas Udayana
Tim Penulis Resume:
- Jerry Fernandi
- Megi Andika
- Muhammad ramadhoni Saputra
- Wisnu Adi witjoro
Jendelakita.my.id – "Progresif dan revolusioner! mungkin dua kata ini juga tepat menggambarkan buku "Sosiologi Kehidupan Sehari-hari" karya Wahyu Budi Nugroho, sosiolog Universitas Udayana. Diterbitkan oleh Sanglah Institute, buku setebal halaman ini membongkar fenomena budaya populer dari SpongeBob hingga budaya alay—melalui kacamata sosiologi dengan gaya bahasa segar nan akademis.
Progresif dan revolusioner!". Itulah dua kata yang kerap digunakan presiden pertama kita, Soekarno, guna merepresentasikan suatu perubahan secara cepat dan mendasar ke arah yang lebih baik. Tak pelak, beberapa dekade pasca sepeninggal beliau, bangsa Indonesia mengalami perubahan yang cepat dan mendasar dalam berbagai lini kehidupan, sedari sosial, politik, ekonomi, hingga budaya. Sarat diakui memang, penilaian akan baik-buruk serangkaian bentuk perubahan tersebut bersifat diskursif. Artinya, berkelindan dengan ideologi maupun sudut pandang pihak-pihak yang berkepentingan dengannya.
Satu di antara bentuk perubahan tersebut yang agaknya kuat-mengemuka dalam beberapa tahun terakhir ini adalah penggunaan "budaya alay" oleh mereka yang kerap dicap sebagai "generasi alay" atau alayers 'anak-anak alay. Diakui atau tidak, budaya alay telah memiliki momentum tersendiri dalam sejarah perkembangan budaya bangsa ini. la merupakan fakta budaya sekaligus fakta sosial yang tak bisa dihindari, disembunyikan, alih-alih ditiadakan mengingat telah menjadi bagian dari perjalanan masyarakat kita, utamanya generasi muda.
Lebih jauh, tulisan ini berupaya mengambil posisi yang tegas di tengah pro-kontra yang terjadi antara sebagian pihak yang menerima budaya alay vis-à-vis sebagian lain yang menolaknya. Keyakinan penulis akan budaya sebagai perihal yang lumer dan dinamis. beriniplikasi pada sebentuk premis bahwa budaya alay pun sarat dihargai dan diberikan tempat tersendiri dalam khasanah kebudayaan berbicara alay dipraktikkan. Sedang, penggunaan kata atau kalimat yang diplesetkan dalam gaya berbicara alay agaknya sebagaimana kerap kita dengar akhir-akhir ini: kalimat "ah, masa sih? menjadi "amacacih?"; kata "serius" menjadi "ciyus"; serta kalimat "demi apa?" menjadi "miyapah?" Budaya alay sering dianggap sebagai bentuk kemunduran berbahasa, tapi sebenarnya ia merepresentasikan kreativitas generasi muda dalam mengekspresikan identitas. Fenomena seperti penulisan "f4c3bv9h" untuk "facebook" atau "ciyus" untuk "serius" bukan sekadar penyimpangan, melainkan bentuk adaptasi linguistik di era digital. Justru inilah yang membuat bahasa terus hidup dan dinamis, merespons perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya. Banyak yang mengkhawatirkan budaya alay akan merusak EYD, tapi perlu diingat bahwa bahasa selalu berkembang melalui percabangan kreatif. Lihat saja bagaimana Malaysia menerima kreolisasi bahasa seperti "fesbuk" atau "snek" sebagai bagian dari keseharian. Alih-alih ditolak, bahasa alay bisa diposisikan sebagai varian informal yang memperkaya khasanah komunikasi, selama pemakai memahami konteks penggunaannya. Yang menarik dari budaya alay adalah ritualnya yang lengkap, mulai dari gaya berbicara, penulisan, hingga penampilan. Ini sesuai dengan analisis Hebdige tentang subkultur, di mana semakin kompleks ritual sebuah budaya, semakin besar potensinya untuk bertahan dan berkembang. Bandingkan dengan budaya punk atau gothic yang justru diakui secara global karena kekhasannya.
Generasi muda Indonesia sebenarnya punya peluang menjadikan budaya alay sebagai identitas unik, bukan sekadar tren sesaat. Sayangnya, stigma negatif dari sebagian masyarakat justru membuat potensi ini terhambat. Padahal, jika dilihat lebih jernih, alay adalah bentuk resistensi sekaligus inovasi terhadap norma yang ada. Tuduhan bahwa alay merusak bahasa Indonesia terlalu simplistis. Bahasa bukanlah entitas statis, melainkan sesuatu yang terus berevolusi melalui percampuran dan penemuan baru. Alih-alih melarang, yang lebih penting adalah membangun kesadaran kritis tentang kapan bahasa formal diperlukan dan kapan bahasa kreatif seperti alay bisa digunakan.
Di era media sosial, gaya komunikasi alay justru menemukan momentumnya. Platform seperti TikTok atau Twitter menjadi ruang eksperimen linguistik yang subur. Daripada memandangnya sebagai ancaman, lebih baik kita melihatnya sebagai cerminan bagaimana generasi Z menegosiasikan identitas mereka di ruang digital. Pada akhirnya, budaya alay patut diapresiasi sebagai bagian dari dinamika kebudayaan Indonesia. Daripada memperdebatkan benar-salahnya, lebih produktif jika kita memahami akar kemunculannya dan potensi yang dibawanya. Bagaimanapun, sejarah membuktikan bahwa apa yang dianggap "rendah" hari ini, bisa jadi akan diakui sebagai warisan budaya yang berharga di masa depan.