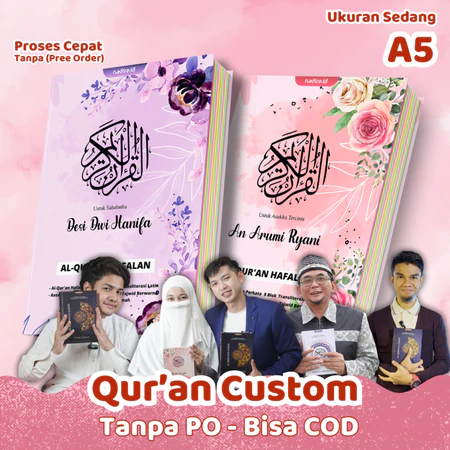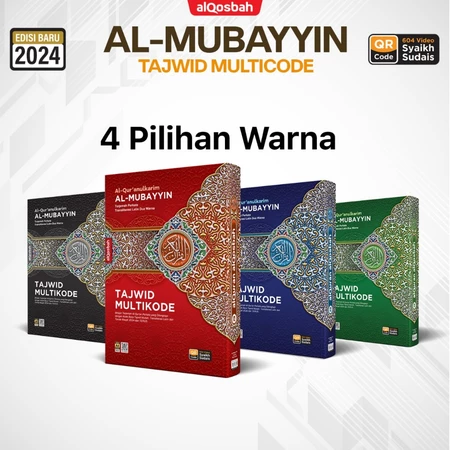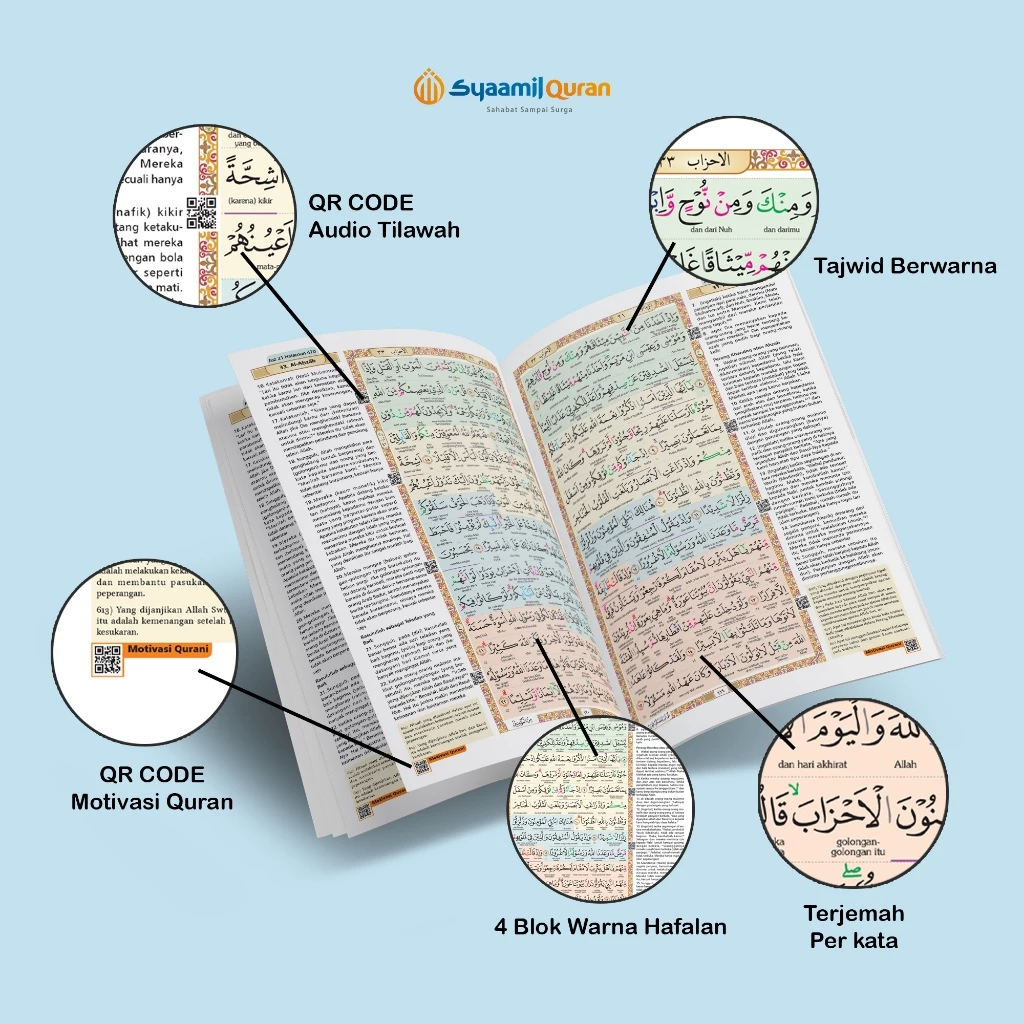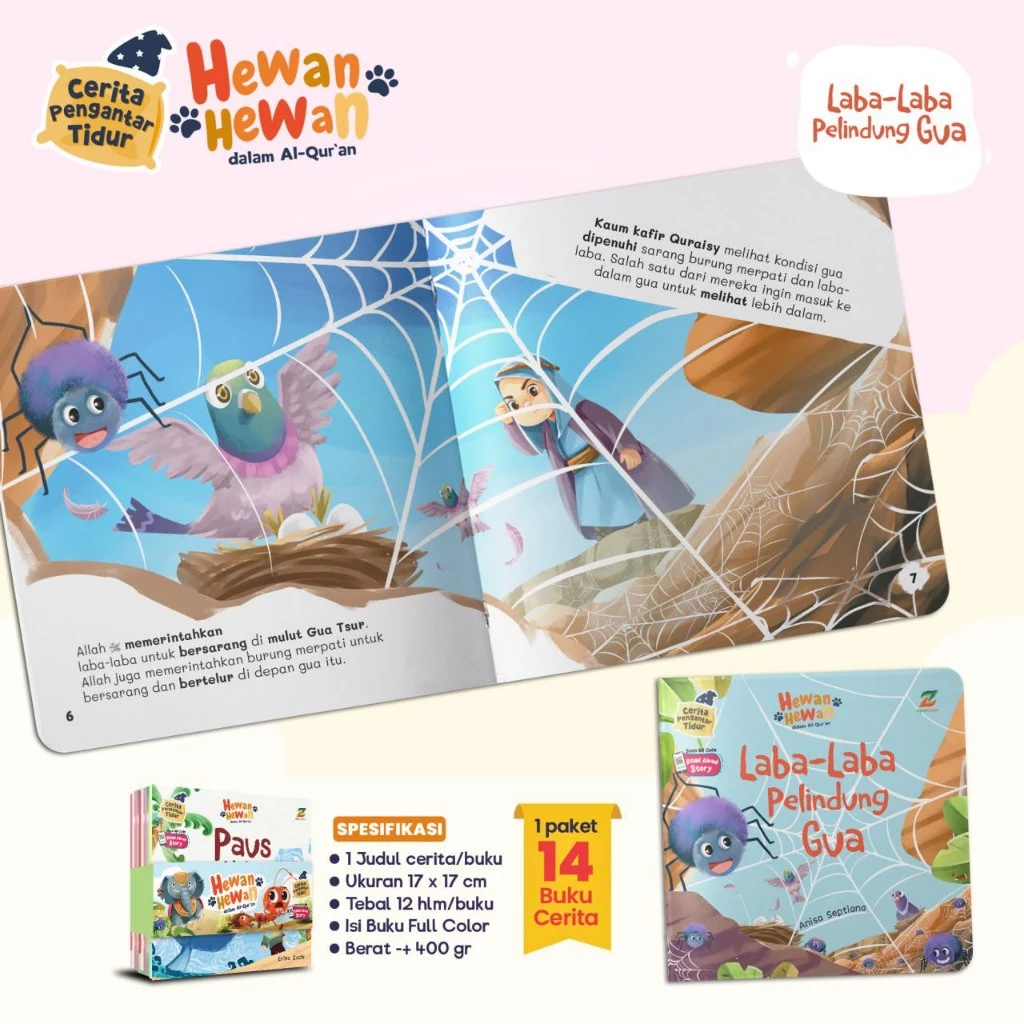Identik kah Masyarakat Hukum Adat Dengan Indigenous Peoples
Jendelakita.my.id - Di dunia akademik sekalipun ada kegalauan dalam mempergunakan istilah istilah yang maknanya saling bertumpang tindih, tapi mempunyai konotasi yang berbeda beda. Kegalauan ini juga berjumpa dengan kita membicarakan mengenai masalah masalah yang ada kaitannya dengan masyarakat hukum adat yang diakui keberadaanya okeh UUD 45 ( Pasal 18 B, ayat (1) dan (2) perubahan kedua). Selama ini kita mengenal, di samping masyarakat adat dan masyarakat hukum adat, juga ada masyarakat suku terasing, atau masyarakat suku terbelakang, atau juga suka disebut dalam konotasi sosiologis nya masyarakat marginal dan terpinggirkan. Dulu di zaman kolonial bahkan juga dikenal ada istilah " suku primitif," yang sekarang kayaknya sudah ditinggalkan karena konotasi nya yang de rogatori, insulting, menghina. Tetapi juga ada istilah pribumi dan non pribumi.
Lalu semua itu digalaukan lagi dengan kita juga mengenal istilah ' Indigenous Peoples ", yang disebut dalam UN Declaration on the Right of Indigenous Peoples, yang telah disahkan pada SU PBB 13 September 2007, dan juga disebut dalam konvensi ILO 169 tahun 1989 .
Pertanyaan mendasar adalah, apakah yang dimaksudkan dengan Indigenous Peoples itu semua masyarakat hukum adat pada semua tingkat perkembangan nya, yang untuk kita berarti semua warga pribumi asli di manapun mereka berasal dan berada di Indonesia ini, ataukah terbatas kepada masyarakat suku terbelakang atau terasing belaka yang adalah kelompok ekslusif dari masyarakat hukum adat itu - yang karena kondisi ekosistem nya hidup menyendiri dalam keadaan terbelakang dan terasing dari kelompok masyarakat hukum adat lainnya yang sudah membaur dan berinteraksi. Di negara negara lain di dunia ini kecenderungan nya adalah bahwa yang dimaksud " Indigenous Peoples itu bukan semua masyarakat asli pribumi, tetapi adalah, dan hanya lah, mereka yang terpinggirkan secara ekosistem itu, yang karena nya terbelakang dan cenderung menutup diri.
Secara etno-nasionalisme sosiolografis kitapun memang membedakan antara kedua kelompok masyarakat hukum adat ini, yang sudah terintegrasi dan yang menyendiri. Di hampir setiap pulau atau gugusan pulau di Indonesia kita masih mengenal suku suku yang kita anggap dan bahkan perlakuan sebagai suku terbelakang atau terasing itu. Di Sumatera saja, di gugusan pulau pulau di lepas pantai barat ada masyarakat hukum adat Mentawai dan Enggano, yang dahulu pun masyarakat Nias biasa dimasukkan ke dalamnya. Di daratan Sumatera sendiri ada suku Talang Mamak, Sakai, Suku Kubu atau anak dalam, orang laut, dan lain lain. Di Jawa ada orang Badui, orang Tengger, di Kalimantan ada orang Dayak dengan belasan suku suku. Di Sulawesi dan Indonesia timur lainnya ada sekian banyak suku suku yang diklasifikasikan sebagai suku terasing atau terbelakang itu. Lalu di Papua, kecuali yang sudah turun ke kota kota, kebanyakan yang masih tinggal di daerah daerah pegunungan masih dianggap dan diperlakukan sebagai orang suku terasing atau terbelakang..
Sekali lagi, apakah mereka mereka yang kita sebut sebagai suku terkebelakang dan terasing ini saja yang dianggap dan klasifikasi sebagai Indigenous Peoples ataukah termasuk semua bangsa pribumi yang lahir dan dibesarkan di bumi Indonesia ini.
Apakah yang dimaksud dengan "kesatuan masyarakat hukum adat" beserta hak hak tradisional nya, seperti dalam pasal 18 B ayat 1 dan 2 UUD 45 itu, adalah kelompok masyarakat pribumi yang masih tinggal di desa desa asli dan tunduk kepada hak hak tradisional nya, ataukah juga yang sudah pindah ke perkotaan tapi masih mempunyai ikatan batin dan sosial budaya dengan kampung halamannya, seperti kebanyakan penduduk kota di manapun di Indonesia ini masih berstatus seperti sekarang ini. Pulang mudik setiap hari lebaran dalam jumlah tak terkira kan, hanya contoh nyata dari fenomena dimaksud. Sementara bermacam corak pembangunan yang dilakukan di kampung halaman adalah juga hasil buah tangan dari usaha perantau itu.
Mereka berpindah ke kota bukan untuk tujuan migrasi permanen tapi dalam artian " merantau mencari rezeki" yang ikatan batin di kampung halaman tidak terputus. Karena nya mereka masih mengisi adat dan tunduk pada hukum adat yang berlaku di kampung halaman masing masing. Dan pertanyaan nya, bagaimana dengan mereka yang secara fisik dan sudah tidak berada di daerah hukum adat nya lagi tetapi punya hubungan batin dan sosial budaya dengan kampung halaman yang ditinggalkannya itu.
Lalu karena Pasal 18 B ayat 1 dan 2 UUD 45 menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, sendirinya akan menggugah Ara Sultan dan Raja yang tidak lagi memiliki kekuasaan memerintah wilayah kuasa adatnya untuk berupaya meng-klaim dan menghidupkan kembali hak hak khusus atau istimewa nya itu.
Lalu ke mana kita akan dibawa oleh diakuinya satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa itu?.
Ini semua, dengan sendirinya, mengharuskan kita untuk menjurus kannya kepada pengklasifikasian dan penuangan nya dalam bentuk undang-undang seperti yang diinginkan oleh bunyi pasal 18 B UUD 45 itu.***
*) Penulis adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Sumatera Selatan